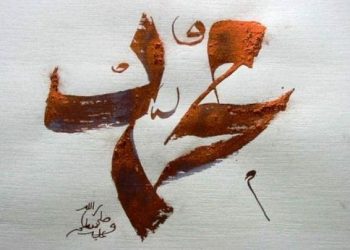Data dan Reputasi
Data penelitian yang benar tentu akan memberikan banyak pengaruh, ia dapat dijadikan sebagai landasan konsepsional bagi banyak hal mulai dari; menjelaskan sesuatu fenomena, merekayasanya hingga memprediksi segala kemungkinan yang akan terjadi setelahnya. Itu sebabnya ada istilah “garbage in, garbage out” di dalam prosedur pengambilan data penelitian. Isitilah ini mempertegas pentingnya kualitas data yang diambil, jika data yang diambil adalah sampah maka data yang dihasilkan juga akan menjadi sampah atau dengan istilah lain tidak memiliki makna.
Dengan kata lain, mutu atau kualitas data akan memberikan pengaruh pada reputasi hasil penelitian. Kemampuan mencari, memperdalam dan mengelola data penelitian inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama agar laporan penelitian yang dihasilkan bisa lebih berkualitas dan autentik. Sebab selama ini kita masih terjebak dengan bentuk Insularitas akademik; yaitu satu bentuk keabaian atau ketidakpedulian terhadap ide, gagasan, budaya dan persoalan-persoalan yang ada di luar dirinya. Bentuk insularitas akademik ini menurut Burhani (2023) dapat dilihat dari masih minimnya ilmuan Indonesia yang diakui reputasinya secara global dalam bidang Indonesian Studies (kajian tentang Indonesia).
Contoh nyata dari insularitas akademik seperti banyak teori ilmu sosial yang lahir dari studi tentang Indonesia, tetapi bukan hasil karya ilmuwan Indonesia. Teori tentang Dualitas Ekonomi (perekonomian ganda) yang memperlihatkan dikotomi antara ekonomi modern dan ekonomi tradisional; justru dihasilkan oleh JH Booke. Dan hingga sekarang konsepsi Booke ini masih banyak dipakai untuk menjelaskan fenomena dualitas ekonomi di negara-negara berkembang kawasan Asia. Tidak hanya Booke, teori tentang Imagined Community dalam konsepsi nasionalisme Indonesia dan Asia Tenggara juga dihasilkan oleh Ben Anderson. Termasuk karya-karya Geertz yang banyak membicarakan tentang masyarakat Indonesia.
Tentu ada banyak variabel yang bisa ditempatkan dalam menjelaskan permasalahan ini. Beberapa orang percaya bahwa kondisi ini disebabkan oleh birokrasi akademik yang masih konservatif, ada yang berkeyakinan bahwa ini disebabkan budaya dan mental akademik yang masih bersifat feodal. Belum lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penghasilan rendah para akademikus, meski kampus -dalam banyak kasus -telah berubah menjadi industri pendidikan tetapi banyak dari akademikusnya justru dibayar di bawah UMR (Upah Minimum Regional). Jebakan ini semakin diperparah ketika prosedur administrasi dalam penelitian jauh lebih diutama dari pada produksi pengetahuan itu sendiri. Jadi wajar jika data yang dihasilkan tidak maksmimal karena jebakan-jebakan birokrasi administrasi penelitian masih begitu kuat.
Baca Artikel Terkait:
Belakangan ada upaya untuk mengurangi jebakan birokrasi administrasi penelitian dengan membuat kebijakan penelitian yang berbasis pada luaran (out-put) berupa publikasi pada Jurnal Terindek di Sinta-2 atau Sinta-3. Pada beberapa kasus terdapat juga hasil penelitian yang harus dipublikasi pada Jurnal Internasional bereputasi yang terindeks pada Scopus. Kebijakan ini pada satu sisi mengurangi beban administrasi pelaporan, tetapi di sini lain kebijakan ini juga menimbulkan polekmik baru bagi para peneliti. Jadwal tunggu dan antrian yang panjang pada publikasi jurnal terkadang jauh lebih lama dibandingkan permintaan pelaporan luaran penelitian yang diharuskan selesai dalam jangka waktu satu tahun.
Belum lagi, beberapa draf jurnal hasil laporan penelitian ditolak oleh publisher jurnal hanya kerena ketidaksesuaian tema/topik pada jurnal, logika isi laporan penelitian yang tidak tepat antara latar belakang dan pembahasan. Kondisi ini menjadi tanda bahwa kemampuan menulis kita belum sesuai dengan standart global sehingga beberapa dari kita melakukan vanity press; yaitu suatu bentuk penerbitan yang tidak mengedepankan kualitas tetapi lebih dikarenakan penulis membayar publikasi.
Tidak berhenti sampai di situ saja, untuk mencapai reputasi dari publikasi hasil penelitian; beberapa kampus membuat kebijakan yang mengharuskan mahasiswa Magister dan Doktoral untuk menulis pada jurnal internasional (baik yang terindeks Scopus maupun yang tidak) dengan mengandeng para dosen pembimbing/promotor sebagai penulis kedua, ketiga dan keempat. Tentunya dengan menggandeng para dosen pembimbing/promotor pada publikasi jurnal maka secara otomatis para akademisi tersebut mendapatkan efek peningkatan jumlah publikasi pada data base mereka dan juga data base universitas. Kondisi ini tentu menguntungkan bagi universitas untuk menaikan reting publikasi internasional mereka sehingga kelompok akademisi yang “malas” melalukan penelitian dan penulisan jurnal dapat “menumpangkan” kewajiban mereka kepada kelompok mahasiswa yang hendak memperoleh gelar master dan doktor di universitas tersebut.