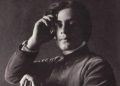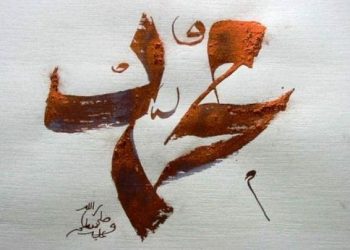Judul : DISKURSUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN DARI ORDE BARU HINGGA PASCAREFORMASI
Penulis : Mujahiddin, S. Sos, MSP
Penerbit: UMSU Press
Tebal Buku: 198 halaman
Cetakan: Cetakan Pertama Agustus 2022
“Because they claim to be concerned with the welfare of whole societies, governments arrogate to themselves the right to pass off as mere abstract profit or loss the human unhappiness that their decisions provoke or their negligence permits. It is a duty of an international citizenship to always bring the testimony of people’s suffering to the eyes and ears of governments, sufferings for which it’s untrue that they are not responsible. The suffering of men must never be a mere silent residue of policy. It grounds an absolute right to stand up and speak to those who hold power.”
( Michel Foucault )
Tanpa disadari, dalam rutinitas kehidupan yang monoton sebuah kata terkadang menjadi mantra. Makna kata tersebut dipahami dan dipercaya begitu saja tanpa reserve.
Misalnya tentang kata “pembangunan.” Secara kebahasaan, kata “pembangunan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “proses, cara, perbuatan membangun.” Ia dipandang menggambarkan sesuatu yang melulu baik, sehingga wajib dilaksanakan. Tapi apa jadinya jika kata “pembangunan” telah menjadi mantra?
Pada hal, faktanya pembangunan tidak selalu melahirkan sesuatu yang konstruktif, sesuai dengan apa yang diharapkan (das sollen) . Tidak jarang, pada tataran das sein, pembangunan justru kemudian memunculkan pelbagai implikasi destruktif, seperti ironi, distorsi dan anomali.
Fenomena inilah yang coba diungkap oleh Mujahiddin S.Sos MSP, akademisi FISIP UMSU melalui buku yang berjudul “Diskursus pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Dari orde Baru Hingga Pascareformasi”.
Dalam buku ini terbongkar, betapa wajah pembangunan ternyata tidak selalu “mulus”, tapi juga tak jarang justru memperlihatkan kesan “kusam”.
Secara lugas, buku ini mengulas dan menganalisis fenomena pembangunan – khususnya pemberdayaan masyarakat – yang ada di wilayah perdesaaan dari masa Orde Baru hingga Pascareformasi.
Menariknya, dalam mengkaji pemberdayaan masyarakat desa penulis menggunakan pendekatan diskurus yang diajukan oleh Michel Foucault, sebuah pendekatan yang belum banyak dipakai oleh peneliti lain dalam melihat atau menganalisis praktik pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
Secara sederhana buku ini membahas tiga hal yaitu: pertama, kemunculan diskursus dan diskursus sebagai kuasa pengetahuan. Kedua, ruang lingkup pemberdayaan masyarakat. Ketiga, bentuk diskursus pemberdayaan masyarakat pada masa Orde Baru dan Pasca Reformasi. Keempat, Implikasi Diskursus Pemberdayaan Dalam Pembentukan Manusia Sejahtera.
Keempat gambaran di atas kemudian relevan untuk diletakkan dalam dua tataran, praktis dan akademis. Pada tataran praktis, diskursus tentang pemberdayaan masyarakat desa secara nasional terus mengalami berbagai perubahan dan perubahan tersebut memberikan dampak pada konteks lokal desa.
Selain itu, diskursus pemberdayaan masyarakat desa pada konteks lokal desa juga tidak selamanya sama. Perubahan aktor, elit politik desa tentunya berdampak pada keberlangsungan praktik pemberdayaan masyarakat desa.
Pada tataran akademis, konsep diskursus dalam praktik pemberdayaan masyarakat masuk pada wilayah perspektif post-struktural. Perspektif ini pada dasarnya bertumpu pada usaha untuk melacak akar dari berbagai ide, gagasan dan pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat yang diwacanakan dan dipraktikan pada satu wilayah. Perspektif ini kemudian menempatkan perbubahan wacana sebagai alat utama untuk meningkatkan kesadaran dan mengkontrol pengetahuan masyarakat agar mau menjadi lebih berdaya.
Analisis diskursus Foucault baik dalam terminologi post-struktural maupun post-modernisme pada dasarnya menempatkan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan dalam satu arena praktik sosial.
Harus diakui, buku ini secara general dan utuh akan menjabarkan bentuk relasi kuasa pengetahuan global-nasional pada praktik pemberdayaan masyarakat perdesaan dan menemukan pembentukan dari setiap episteme diskursus pada setiap masa kekuasaan di Indonesia; dari masa Orde Baru hingga Pascareformasi.
Dalam buku ini penulis mengungkapkan, bahwa kegagalan pembangunan di sektor pertanian dan terciptannya kemiskinan di desa menjadi tanda adanya diskursus kuasa pengetahuan yang tidak menempatkan pengetahuan lokal petani desa sebagai basis argumentasinya. Artinya diskursus modernisasi di sektor pertanian berhasil menggeser pengetahuan tradisional.
Dan anehnya, diskursus itu terus diproduksi dan dikontrol oleh rezim penguasa dan dilegitimasi oleh kelompok intelektual, sehingga diskursus tersebut bisa bertahan menjadi epistime.
Dalam “Catatan Akhir” buku ini, penulis mengatakan bahwa pembentukan diskursus pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia terus mengalami berbagai perubahan. Hal itu terjadi karena adanya perubahan epistime pada setiap masa pemerintahan, baik pada amsa orde baru, reformasi dan pascareformasi.
Perubahan epistime pada diskursus pemberdayaan masyarakat disebabkan adanya perubahan penegetahuan dan kekuasaan. Sehingga nilai yang menjadi kebenaran dalam praktik pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh legitimasi pemerintah berkuasa yang “berkedok” untuk kesejahteraan rakyat, namun sebenarnya lebih mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok dan atau lembaga-lembaga donor.
Pada akhirnya, dalam buku ini penulis menyimpulkan, bahwa keseluruhan diskursus pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk peneingkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya kelompok petani tidak terwujud secara nyata. Justru yang terjadi adalah kemiskinan yang paling dalam dan terus dirasakan oleh kelompok petani.
Menurut penulis, hal ini disebabkan sejak awal pembentukan diskursus pemberdayaan masyarakat tidak pernah menempatkan diskursus lokalsebagai pengetahuan utama. Pemerintah pusat dan Lembaga global yang terkait, seolah-olah paling tahu kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat desa atau petani.
Dengan dikuasainya diskursus pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah pusat dan Lembaga-lembaga global, maka praktik pemberdayaan masyarakat di pedesaan juga bersifat top-down dan diatur oleh berbagai regulasi pemerintah pusat yang tidak pernah menempatkan penegetahuan lokal dan kebutuhan lokal sebagai basis utama pelaksanaan praktik pemberdayaan masyarakat. Pada konsep ini, nilai dan praktik pemberdayaan masyarakat akhirnya bersifat universalisme dan mengabaikan kasus-kasus lokal
Seperti yang dituturkan pada epilog Prakata buku ini, penulis berharap buku ini dapat menjadi rujukan yang menarik bagi kelompok-kelompok yang fokus mengkaji dinamika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, seperti dari kalangan akademisi, pemerintahan maupun non-pemerintahan serta berbagai kelompok kepentingan lainnya.
Selaras dengan harapan penulis, apa yang disajikan di dalam buku ini memang pantas menjadi enter-point bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik membuat kajian tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. (*)
Peresensi: M. Risfan Sihaloho