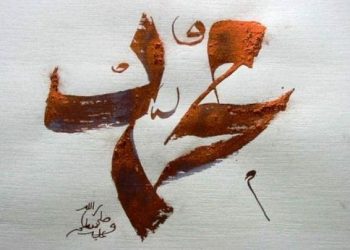Oleh: Mujahiddin
(Associate Professor bidang Studi Pembangunan di FISIP UMSU)
Kini, penjajah itu sudah pergi, rezim terus berganti. Tapi budaya kolonial itu, rasanya sulit sekali terkikis dari dalam diri anak bangsa.
Merdeka; kata itu bukan hanya sebatas kumpulan huruf saja. Sebagai sebuah kata yang tersusun, ia mempunyai historis, makna dan nilai yang tersembunyi. Terkadang ia mempunyai power; kemampuan untuk melecuti semangat perlawanan terhadap ketidakadilan.
Secara defenitif, kata merdeka dapat diartikan dalam tiga bentuk; pertama, lepas dari belenggu dan penjajahan. Kedua, diartikan sebagai tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ketiga, merdeka berarti tidak terikat, tidak bergantung pada pihak atau orang tertentu.
Ketiga bentuk defenisi di atas, pada subtansinya dapat merujuk pada konteks lepas dari segala bentuk belenggu baik yang bersifat penjajahan (kolonialisme) dan atau segala bentuk ketergantungan (dependensi). Jika begitu, maka sulit rasanya bagi kita untuk memperoleh kemerdekaan yang hakiki? Yaitu lepas dari berbagai belenggu dan ketergantungan dari pihak manapun. Mengingat dalam segala bentuk dimensi kehidupan, kita semua pada dasarnya terikat dalam satu fakta sosial bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.
Pada realitas sosial yang lebih abstrak seperti negara, hukum yang sama juga berlaku; “tidak ada negara yang bisa memenuhi kehidupan warganya secara independent. Setiap negara tetap membutuhkan negara lain.” Di sini keterikatan atau ketersaling gantungan terlihat. Ia seolah sudah menjadi hukum alam yang tidak bisa dilepaskan. Selama masih berada di dunia dan mengagungkan nilai-nilai keduniawian, maka rasa-rasanya sulit bagi setiap kita untuk bisa mengecap kemerdekaan secara substantif. Bukankah kata merdeka itu sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, maharddhika yang artinya telah bebas dari soal keduniawian?
Suara Tanpa Ruh
Kata merdeka secara luas digunakan pada periode waktu pergerakan kebangsaan yaitu dari tahun 1908 hingga 1945, terutama dalam konteks kehendak untuk bebas dari penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi momen puncak di mana pekik ‘merdeka’ tidak hanya sebatas suara yang lantang, tetapi juga menjadi simbol perjuangan dan indentitas kolektif nasional. Bahkan pada 31 Agustus 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa pekik ‘merdeka’ sebagai salam nasional.
Namun kini, pekik ‘merdeka’ itu tidak lagi sesakral dahulu. Setiap kali pekik itu diucapkan oleh elit politik, maka akan ada batin di dalam diri rakyat yang bertanya; apa iya kita merdeka? Jangan-jangan kemerdekaan ini hanya dinikmati oleh segelintir ‘mereka’ yang berada di lingkar kekuasaan?
Pertanyaan-pertanyaan ini selalu terulang setiap kali momen perayaan kemerdekaan akan dilaksanakan.
Rakyat kebanyakan memang happy dengan beragam perayaan kemerdekaan di sudut-sudut gang perkotaan, di lapangan-lapangan perkampungan, yang diselenggarakan secara partisipatif, urungan dan gotong royong. Ada beragam lomba, pawai dan karnaval, hias kampung, hingga pertunjukan musik keyboard.
Di tengah situasi itu semua, rakyat sesungguhnya sadar; ketika anak-anak mereka berlomba makan kerupuk, di sisi yang lain ada anak-anak elit politik sibuk berlomba makan tambang. Ketika anak dan suami mereka sibuk berlomba panjang pinang untuk memperoleh hadiah di pucuk pohon pinang, maka para elit politik dan pejabat negara juga sibuk bekerjasama membentuk kelompok, saling injak kepala teman untuk bisa mencapai puncak kekuasaan.
Begitulah realitas yang dirasakan rakyat. Tidak ada kejujuran di dalam diri para elit, tidak ada kesederhanaan. Pidato yang berapi-api itu hanya kamuflase untuk menyenangkan hati publik, untuk mendapat sorak sorai dan standing applause yang nantinya akan diberitakan di media massa.
Rakyat sesungguhnya sadar; ketika anak-anak mereka berlomba makan kerupuk, di sisi yang lain ada anak-anak elit politik sibuk berlomba makan tambang.
Kesederhanaan juga begitu, ia hanya ditampilkan ketika mendekati tahun pemilihan umum. Menyapa rakyat, merangkul orang tua, memegang kepala balita. Seolah paling tahu dan paling merasakan penderitaan mereka.
Jadi pekik merdeka itu telah kehilangan ruhnya. Orang yang berteriak merdeka itu bukan orang yang benar-benar ingin memerdekakan rakyatnya; melepaskan mereka dari belenggu dan beban kehidupan yang terasa semakin berat. Merdeka itu kini hanya sebatas suara; suara tanpa ruh.
Dekolonialisasi
Jika secara subtantif, mungkin saja kita belum benar-benar bisa mengecap kemerdekaan, tetapi setidaknya secara praktis kita sudah berada di satu fase atau tahap lepas dari penjajahan (kolonialisme), dan itu patut untuk disyukuri. Saat ini pekerjaan terbesar kita adalah berupaya untuk terus menerus menghilangkan warisan dari kolonialisme yang masih hidup dan menetap di dalam praktik sosial-politik kita.
Ungkapan terjajah oleh bangsa sendiri terkadang ada benarnya. Presiden Soekarno sudah mengingatkan hal ini sejak awal-awal negara ini berdiri. Budaya kolonial masih melekat pada sistem dan tata kelola birokasi kita. Siapapun yang masuk ke dalam sistem itu, ia akan berubah menjadi kolonial; menjajah, menipu, korup, kolusi, nepotis, rakus dan eksploitatif. Good governance hanya menjadi isapan jempol. Para birokrat yang bekerja di dalam sistem birokrasi itu sendiri tidak lahir dari merit sistem yang utuh. Kebanyakan dari proses transaksi, jual beli jabatan berdasarkan kontribusi ekonomi dan sosial-politiknya.
Sistem birokrasi tersebut tentu tidak berdiri sendiri, ia menjadi bagian tidak terpisahkan dari wilayah politik yang saat ini serba pragmatis, transaksional dan korup. Budaya-budaya kolonial hidup dan tumbuh subur di wilayah ini. Hubungan patron-klien antar elit dan pemilih, korupsi, dominasi otoritatif yang sentralistik dan politik dinasti; adalah peninggalan-peninggalan kolonial yang masih melekat hingga kini. Penjajah sudah pergi, rezim terus berganti. Tapi budaya kolonial itu, rasanya sulit sekali terkikis dari dalam diri anak bangsa.
Pekerjaan terberat kita pada saat ini adalah mengurangi efek panjang dari kolonialisme yang sudah terinternalisasi ke dalam berbagai tatanan kehidupan bernegara. Kita harus menyusun ulang proses dekolonialisasi dengan cara yang benar; the history of intelektualisme yang kita miliki harus dilacak dan disusun ulang sebagai guiden pembangunan negara.
China sudah memulainya, pembangunan mereka tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan refleksi mendalam dan melihat kembali sejarah intelektual mereka untuk mencari inspirasi dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada tantangan modern. Mereka mempelajari kembali pemikiran Konfusius, yang menekankan pentingnya harmoni sosial, pendidikan, dan pemerintahan yang baik. Pemikiran-pemikiran ini ternyata relevan dalam konteks membangun masyarakat yang stabil dan sejahtera. Lalu mengapa kita tidak melakukannya? Bukankah kita negara dengan kekayaan tradisi dan prinsip hidup yang banyak?
Dengan kata lain, proses dekolonisasi tidak hanya berhenti pada kemerdekaan politik, tetapi juga memerlukan upaya untuk membebaskan diri dari warisan kolonial dalam berbagai bidang kehidupan.
Jika ini tidak dilakukan, maka kemerdekaan “sampai kapanpun” hanya akan menjadi miliki ‘mereka’ yang berada di lingkaran kekuasaan. (*)