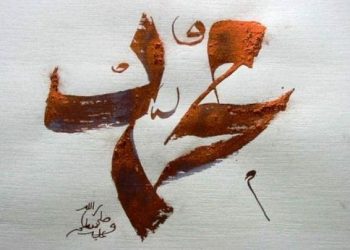Duka Sigapiton itu sebenarnya begitu sederhana dan sangat mudah diantisipasi jika saja ada penghargaan terhadap komunitas. Ia berhulu pada kesemrawutan hukum terbiarkan dan arus kebijakan tanpa rem atas nama pembangunan, sembari mengedepannya ketakpedulian atas nilai-nilai-lokal. Di sini interaksi ekonomi pinggiran dan ekonomi raksasa melukiskan pertarungan ala David dan Goliath.
Lon Luvois Fuller (1969) benar ketika membagi delapan jalan menuju kegagalan dalam pembentukan UU. Kedelapan jalan itu adalah pertama, tidak ada aturan (kevakuman hukum) atau malah hukum yang ada justru menimbulkan ketidakpastian; kedua, kegagalan untuk mempublikasikan atau memperkenalkan aturan hukum kepada masyarakat; ketiga, aturan berlaku surut yang diterapkan secara tidak pantas; keempat, kegagalan menciptakan hukum yang bersifat komprehensif, kelima, pembentukan aturan yang kontradiksi satu sama lain; keenam, pembentukan aturan yang mencantumkan persyaratan yang mustahil dipenuhi; ketujuh, perubahan aturan secara cepat sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kedelapan, adanya ketidak sinambungan antara aturan dengan penerapannya.
Rasanya, untuk Indonesia, khususnya terkait masalah tanah yang disengketakan di Sigapiton, sangat mudah difahami bahwa dualisme politik pemerintahan sejak Hindia Belanda amat bertanggung jawab atas timbulnya berbagai kelembagaan hak atas tanah yang bersumber pada pertentangan antara Hukum Barat dan hukum adat.
Van Vollen Hoven menyebut hak ulayat sebagai beschikkingrescht yang melukiskan keterkaitan atau hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah itu sendiri. Dengan begitu ada ketegasan tentang hubungan hukum konkrit antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah di dalam wilayah yang didiaminya.
Semestinya tanah adalah wilayah yang dikuasai dan diatur penguasaannya tidak saja oleh negara, tetapi juga wajib merujuk kepentingan seluruh masyarakat adat di indonesia (patuanan di Ambon, pawatasan di Kalimantan, wewengkon di Jawa, prabumian di Bali, tatabuan di Bolaang mongondow, limpo di Sulawesi selatan, nuru di Buru, ulayat di Minangkabau, paer di Lombok, golat di Toba, dan lain sebagainya). Apa yang bisa menjelaskan kesan lebih mulia dan lebih manusiawinya belanda yang menjajah 350 tahun dibanding rezim pemerintahan yang silih berganti? Reforma agraria tak dianggap penting.
Namun RUU Pertanahan yang kini menjadi kontroversi dengan begitu teganya tidak menganggap penting reforma agraria karena kelihatannya hanya menyalin isi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Padahal RUU Pertanahan diharapkan memuat prinsip-prinsip reforma agraria, subjek prioritas pemanfaatannya siapa, objeknya apa, dan bagaimana memecahkan konflik lahan (Maria Sumardjono, Guru Besar Hukum Agraria, UGM, 2019).
RUU yang sama juga menegaskan perpanjangan HGU hingga 90 tahun (pasal 25). Perpanjangan HGU yang sudah diberikan selama 35 tahun bisa diperpanjang untuk kedua kalinya sehingga mencapai 90 tahun. Ini seakan menghidupkan kembali praktik politik agraria zaman kolonial. Pasal 36 RUU ini mewajibkan permohonan perpanjangan 5 tahun sebelum hak atas tanah berakhir yang dikhawatirkan menimbulkan masalah baru.
Mekanisme penyelesaian konflik agraria yang komprehensif tidak ada, sehingga berpotensi munculnya pengadilan pertanahan. Ketika satu tanah tidak bisa dibuktikan siapa pemiliknya, otomatis negara memilikinya
Kemudian, apalah gerangan maksud pemerintah ketika nama pemegang izin HGU dirahasiakan? Informasi pemilik hak atas tanah yang dirahasiakan kepada publik (pasal 45 ayat 9) begitu mengherankan.
Ada ancaman pidana bagi korban penggusuran di dalam RUU Pertanahan. Pasal 89 berisi ancaman kriminalisasi bagi masyarakat yang berusaha mempertahankan tanahnya dari penggusuran. Pasal 94 mengancam pidana 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar bagi setiap orang atau kelompok yang menyebabkan sengketa lahan. Menurut YLBHI kasus pertanahan menjadi aduan paling banyak tahun 2018 (300 kasus).
Orang Batak mungkin dikenal sangat kuat memegang adat. Namun dimensi keberlakuannya jauh sekali di bawah ketika dibandingkan dengan adat Bali yang mampu memaksa masyarakat dunia untuk ikut nyepi tak perduli ekonomi lumpuh sehari. Adat Batak tak dihargai sehebat itu di Indonesia dan tak terkecuali di tanahnya (home land) sendiri.
Paradoksnya semua itu terjadi saat kemeriahan fenomena mendunia kebangkitan isu perjuangan martabat. Makin terasa paradoks bahwa selain DKI (tempat sebuah istana berdiri), Bogor (tempat sebuah istana yang lain berdiri) dan Solo (kampung halaman Joko Widodo), mungkin tidak ada daerah yang paling kerap dikunjungi oleh Joko Widodo di Indonesia selain daerah seputaran Danau Toba ini.
Solusi paling utama akan terletak pada perjuangan mengganti paradigma neoliberal yang dianut hampir semua rezim pemerintahan di dunia dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya. Konkritnya, pengembalian kedudukan negara sebagai pengatur pasar dan pemodal, bukan seperti sekarang, negara lebih banyak diatur pasar dan pemodal.
Agar negara berfungsi optimal, yang dalam konteks Indonesia berarti mencapai cita-cita kemerdekaan (melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa), diperlukan pendekatan berbasis revolusi martabat untuk kebijakan. Jika hanya ingin berbangga ria karena kemajuan yang tak menyertakan rakyat, Belanda pun dulu mampu melakukan itu. Itulah maknanya Indonesia merdeka.
Paradigma kuno dan otoriter menyeret-nyeret rakyat ke pembangunan harus dirubah menjadi paradigma demokratis mendekatkan pembangunan kepada masyarakat berbasis pendekatan community organization dan community development.
Agenda revolusi martabat sebagai gejala dunia harus hadir di Sigapiton. Masih merasa perlukah bertanya mengapa perlu ditekankan dalam pengembangan Danau Toba? (*)

Shohibul Anshor Siregar