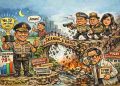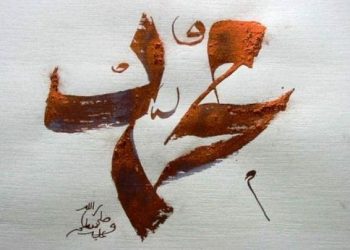Oleh: Shohibul Anshor Siregar
Persinggungan antara politik dan agama telah menjadi topik diskusi dan perdebatan sepanjang sejarah. Banyak teks-teks agama telah ditafsirkan untuk memberikan panduan bagi para pemimpin politik, sementara yang lain menekankan pemisahan antara gereja dan negara.
Dalam agama Kristen, Alkitab berisi ayat-ayat yang telah digunakan untuk mendukung kedua sisi perdebatan ini. Sebagai contoh, Matius 22:21 sering dikutip sebagai bukti pemisahan gereja dan negara: “Karena itu, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah.” Namun, ayat-ayat lain dalam Alkitab menunjukkan bahwa para pemimpin harus dipilih berdasarkan iman dan ketaatan mereka pada ajaran agama.
Dalam Islam, Al-Quran memberikan panduan tentang masalah politik seperti pemerintahan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Hadis juga berisi banyak perkataan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad yang berhubungan dengan politik. Demikian pula, agama Hindu menekankan pentingnya dharma (kebenaran) dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Bhagavad Gita berisi ajaran-ajaran tentang kepemimpinan dan pemerintahan yang menekankan pentingnya bertindak tanpa pamrih untuk kepentingan semua orang.
Dalam beberapa tahun terakhir, kebangkitan partai-partai politik agama di negara-negara Barat telah menjadi topik yang semakin menarik di kalangan cendekiawan dan pembuat kebijakan. Fenomena ini tidak sepenuhnya baru, tetapi telah mendapatkan daya tarik di banyak tempat di mana sebelumnya tidak ada atau marjinal. Beberapa peneliti berpendapat bahwa tren ini dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk penurunan sekularisme yang dirasakan, pertumbuhan keragaman agama, dan kegagalan partai politik yang ada untuk secara memadai menangani isu-isu tertentu yang penting bagi komunitas agama (Barber & Liebman, 2018; Hooghe & Dassonneville, 2018; Kuru, 2019).
Salah satu alasan munculnya partai politik agama di negara-negara demokrasi Barat mungkin terkait dengan perubahan sifat agama itu sendiri. Seperti yang telah dicatat oleh beberapa peneliti, agama di banyak bagian dunia menjadi lebih individualis dan kurang terikat pada institusi dan doktrin tradisional (Casanova, 1994; Davie, 1994). Pergeseran ini mungkin membuat individu lebih mudah mengidentifikasi diri mereka dengan partai atau gerakan politik berbasis agama tertentu yang mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai pribadi mereka.
Penjelasan lain yang mungkin untuk meningkatnya popularitas partai politik agama di negara-negara Barat terkait dengan perubahan sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, beberapa peneliti berpendapat bahwa globalisasi ekonomi dan pluralisme budaya telah mengikis sumber-sumber identitas dan komunitas tradisional, sehingga membuat individu merasa terputus dan kecewa dengan politik arus utama (Hechter & Soltan, 2010; Inglehart & Norris, 2016). Partai politik agama mungkin menawarkan rasa memiliki dan tujuan yang tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat lainnya.
Terlepas dari berbagai penjelasan mengapa partai-partai politik agama mendapatkan tempat di negara-negara demokrasi Barat, masih banyak perdebatan mengenai dampaknya secara keseluruhan terhadap pemerintahan yang demokratis. Beberapa kritikus berpendapat bahwa partai-partai ini merupakan ancaman bagi nilai-nilai demokrasi liberal seperti toleransi dan kesetaraan dengan mengistimewakan satu kelompok agama tertentu di atas kelompok agama lainnya (Kymlicka & Norman, 1994). Yang lain berpendapat bahwa partai politik agama sebenarnya dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dengan mendorong representasi dan partisipasi yang lebih besar di antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Kuru, 2019).
Terlepas dari pandangan seseorang tentang manfaat partai politik agama di negara-negara demokrasi Barat, pertumbuhan dan pengaruhnya yang terus berlanjut kemungkinan besar akan tetap menjadi topik diskusi penting di antara para cendekiawan dan pembuat kebijakan di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, sangat penting bagi para peneliti untuk terus mengeksplorasi fenomena ini secara mendalam untuk lebih memahami penyebab, konsekuensi, dan implikasi potensial bagi pemerintahan yang demokratis. (*)
Rujukan
- Barber, M., & Liebman, R. C. (Eds.). (2018). Religious minorities and democratic consolidation: The cases of Georgia and Armenia. Routledge.
- Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. University of Chicago Press.
- Coogan, M.D., Brettler, M.Z., Newsom, C.A. (Eds.). (2011). The New Oxford Annotated Bible: New Revised Standard Version with the Apocrypha. Oxford University Press.
- Davie, G. (1994). Religion in Britain since 1945: Believing without belonging. Blackwell Publishers.
- Hechter, M., & Soltan, K. E. (2010). Mechanisms of moral disengagement in support of political violence. American Behavioral Scientist, 53(11), 1452-1467.
- Hooghe, M., & Dassonneville, R. (2018). Do religious parties undermine democracy? A comparative analysis of eight European democracies. Party Politics, 24(1), 3-14.
- Inglehart, R., & Norris, P. (2016). Trump and the xenophobic populist parties: The silent revolution in reverse. Perspectives on Politics, 15(2), 443-454.
- Kuru, A. T. (2019). Islamism and democracy in Indonesia: Piety and pragmatism. Oxford University Press.
Kymlicka, W., & Norman, W. (1994). Return of the citizen: A survey of recent work on citizenship theory. Ethics, 104(2), 352-381. - Peters, R. (2016). Religion and Politics: Perspectives from World Religions (Third Edition). Oxford University Press.
- Pouligny, B., Chesterman, S., & Schnabel A. (Eds.). (2011). The Politics of Religion and the Spirituality of Politics: Essays on Peacebuilding. United Nations University Press.
- Ramakrishnan, S., & Chen, V. (2019). Religion and Politics in India. Annual Review of Political Science, 22(1), 167-184.
- Sohail, K., & Awan, M. J. (2019). Islam and Politics: An Overview with Reference to Contemporary Muslim Societies. Journal of Political Studies, 26(2), 351-363.
Penulis adalah Dosen FISIP UMSU, Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut