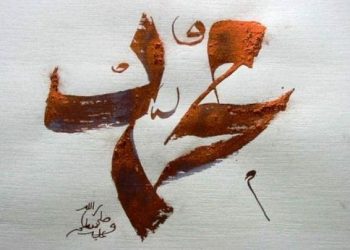Oleh: M. Risfan Sihaloho
Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius.~Najwa Shihab
Adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa bangsa ini begitu akrab dengan hal-hal yang tidak orisinil alias palsu. Virus palsu nyaris menjangkiti hampir seluruh sisi dan lini kehidupan masyarakat kita. Bahkan kecenderungan ini sudah sedemikian sistemik dan masif. Kehidupan kolektif bangsa ini menggeliat dalam dinamika yang penuh kepalsuan.
Ya. Di negeri ini, tercatat sejumlah kasus kepalsuan pernah terkuak dan sempat menjadi isu publik yang menghebohkan, mulai dari kasus uang palsu, ijazah palsu, nabi palsu, pupuk palsu, KTP palsu, dan sebagainya.
Bukan hanya itu, sebenarnya masih banyak kasus lain dengan nama berbeda, tapi sebenarnya konotasinya sama dengan palsu, yang juga pernah terungkap dalam kehidupan masyarakat kita, seperti beras plastik, VCD/DVD bajakan, HP rekondisi, minyak dan miras oplosan, wartawan dan aparat gadungan, berita hoaks, pemimpin boneka dan sebagainya.
Seperti yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah palsu artinya tidak tulen, tidak sah, lancung, gadungan, curang, tidak jujur, sumbang. Dan bila ditelisik, ternyata istilah palsu bukan berasal dari akar bahasa nusantara, tetapi dari bahasa asing: Inggris (false), Belanda (valse), Perancis (faux).
Para sejarawan dan ahli bahasa menduga perkataan palsu masuk kenegeri ini melalui penjajahan belanda, dari valse diindonesiakan menjadi palsu. Padananya dalam bahasa Indonesia adalah lancung, tidak sah, tiruan, bohong, tidak berlaku, dan sebagainya. Pada umumnya mengidentifikasikan keburukan, cacat secara moral.
Situasi dan kondisi bangsa yang dipenuhi oleh kepalsuan ini tentunya sangat membuat kita prihatin. Lantas menyumbul pertanyaan, mengapa sesuatu yang palsu begitu digandrungi oleh bangsa ini? Apakah hal-hal tulen, otentik, orisinil dan genuine sudah menjadi sebegitu langka dan mahal, sehingga musykil untuk dimiliki dan masyarakat kita kurang mengapresiasinya?
Bila kita cermati, sebenarnya benih-benih kepalsuan diam-diam sudah melekat dalam tradisi budaya bangsa ini. Misalnya tradisi bahasa eufemistik dan basa-basi yang mendapat tempat tersendiri dalam kultur masyarakat bangsa kita. Anehnya, justru itu dianggap sebagai bagian dari kekhasan budaya orang Indonesia. Dan jika ada yang tidak mengindahkannya atau gemar berterusterang dalam berbahasa, maka itu dinilai tak punya etika dan sopan santun.
Di bidang sosial-ekonomi, karena pertimbangan kempuan finansial, harus diakui sebahagian dari masyarakat kita kemudian memutuskan lebih suka membeli dan mengkonsumsi barang-barang palsu. Dan sebenarnya, selama barang-barang palsu itu tak menimbulkan efek negatif, merugikan atau membahayakan jiwa konsumen, maka semua tenang-tenang saja, seperti tak ada masalah.
Di sini terlihat, betapa ternyata permisivisme masyarakat terhadap sesuatu palsu adalah wujud dari ketidakberdayaan mereka menyiasati tuntukan kehidupan sosial yang kian pragmatis. Akibatnya, dalam konteks tertentu sesuatu yang palsu kemudian lebih ditolerir, menjadi semacam opsi dan alternatif bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri agar tetap bisa memenuhi tuntutan kehidupan sosial yang semakin hedonistik. Sepanjang dianggap bisa memenuhi standar tuntutan struktur sosial yang dipenuhi prestise, bagi sebagian masyarakat tidak manjadi persoalan menggunakan barang-barang palsu.
Khusus untuk barang-barang konsumsi, selama pemerintah tak mampu dan becus mengendalikan harga, sementara daya beli masyarakat masih rendah, maka dapat dipastikan kecenderungan membeli dan memakai barang-barang palsu akan tetap menjadi kegandrungan.
Sebenarnya kita bukan tidak mengetahui bahwa prilaku memproduksi dan mengkonsumsi barang palsu bukanlah sesuatu yang positif dan baik. Bahkan kita sangat paham hal itu berpotensi menimbulkan resiko–bahkan kadang sampai mengancam nyawa– dan kerugian bagi negara. Tapi ironisnya, sebagian besar dari kita seperti tak peduli, bangsa ini tetap menggandrungi kepalsuan.