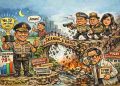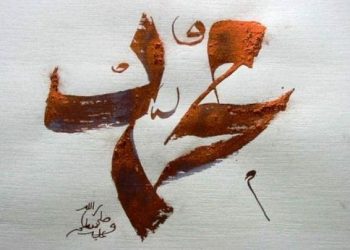Negasi Politik Identitas Islam
Akirnya seluruh dunia adalah rumah bagi Islamofobia, tak terkecuali negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Barat dianggap sebagai satu-satunya tradisi pemikiran yang sah yang mampu menghasilkan pengetahuan dan satu-satunya yang memiliki akses keuniversalitas, rasionalitas, dan kebenaran.
Pengorbitan elit politik Muslim berpendidikan Barat menjadi jalan untuk perumusan regulasi Islam di banyak negara Muslim sebagai cara mengatur identitas yang dianggap sebagai ancaman bagi negara-bangsa. Sebagaimana Salman Sayyid (2014, hlm 8) pernah berucap, tantangan menjadi Muslim saat ini adalah tidak ada ruang epistemologis atau politis untuk identitasnya dan Islamofobia adalah urusan tentang membuat identitas politik Muslim tidak mungkin ada.
Masuknya Islam dalam epistemologi Barat dipandang sebagai sebuah konsep yang akan menggoyahkan tatanan kolonial dan identitas politik Kristen, seperti PartaiDemokrat Kristen Angela Merkel, dapat dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari tatanan politik saat ini, sedangkan ini tidak terjadi atas nama identitas politik Islam.
Rasisme anti-Muslim adalah tindakan bersifat struktural dan dapat bekerja tanpa disadari, yang menjadi bagian dari wacana yang mencerminkan politik identitas esensialis dan reduksionis dari rekan-rekan Barat mereka yang melahirkan konflikasi metris antara yang kuat (powerfull) berhadap-hadapan dengan yang tidak berdaya (powerless). Fenomena lain dalam interaksi ini tak dapat dibantah seringnya termanifestasi dalam berbagai cara permusuhan tak terdamaikan antara elit Muslim yang sekuler dan kebarat-baratan berhadap-hadapan dengan massa Muslim konservatif.
Reproduksi Sistem Kolonial
Dalam Colonial and Post-Colonial Governance of Islam: Continuities and Ruptures, Maussen, Bader dan Moors (2011, hlm 18) berusaha menelusuri kebijakan negara pasca-kolonial terhadap Islam yang mereproduksi pengalaman kolonialis.
Pertama, regulasi pendidikan agama dan otoritas keagamaan.
Kedua, ada pengaturan dan praktik kelembagaan yang bertujuan untuk mengatur properti dan fasilitas.
Ketiga, otoritas dalam konteks kolonial dan pascakolonial berkontribusi untuk mengatur hubungan antara Islam, hukum dan kehidupan sosial. Ini termasuk pengakuan dan/atau kodifikasi hukum Islam dan keseimbangan klaim hukum berbasis agama dengan system hukum adat.
Keempat, ada upaya untuk menciptakan, mengenali dan mungkin melembagakan platform organisasi untuk berbicara untuk Islam dan populasi Muslim, misalnya, dalam bentuk dewan Muslim.
Banyaknya keluhan tentang kriminalisasi ulama di Indonesia akan selalu menjadi perdebatan yang sengit karena dimensinya berayun antara hukum dan politik. Karena elit begitu khawatir dengan potensi Islam politik, maka berbagai fenomena yang menyedihkan akan terus terjadi.
Penting menjadi agenda untuk dijawab bersama oleh umat Islam dan para pengambil kebijakan, di antaranya:
Pertama, bagaimana rasisme anti-Muslim memainkan peran penting dan menentukan justru di dalam masyarakat yang didominasi oleh populasi Muslim seperti Indonesia?
Kedua, bagaimana rasisme anti-Muslim itu secara signifikan berperan penting dalam penentuan kebijakan publik dan dalam proses berkelanjutan klaim-klaim atas ideologi negara yang sekaligus mengundang pertikaian datar maupun berjenjang?
Ketiga, bagaimana rasisme anti-Muslim itu menentukan tata hubungan elit-massa?
Keempat, bagaimana orientasi media di negara-negara berpopulasi mayoritas Muslim itu bekerja sangat efektif memompa semangat rasisme anti-Muslim?
Penutup
Jika semua itu sudah dapat dijawab dengan baik, tak akan ada lagi penistaan model apa pun terhadap Islam, termasuk model yang dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang dan Pendeta Saipudin.
Yakinlah keberanian dari apa yang selama ini disebut buzzeRP dan kalangan pemberi tuduhan negatif seperti Kadal Gurun (Kadrun), terosis dan lainnya akan sertamerta sirna jika umat Islam dan pemerintah mampumenjawab empat pertanyaan yang disebutkan pada bagian sebelum ini, di atas. (*)
Penulis adalah Dosen FISIP UMSU, Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut, Koordinator n’BASIS