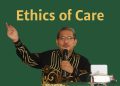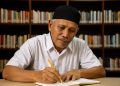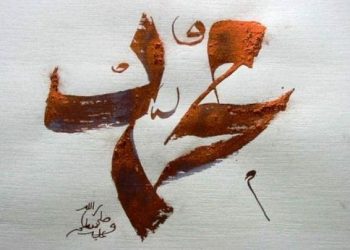Oleh: Shohibul Anshor Siregar
Sebanyak 73 guru besar dari sejumlah universitas yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar Antikorupsi diberitakan kembali meminta Presiden Joko Widodo (Senin 24/5/2021) agar mengawasi tindak tanduk Firli Bahuri cs dan mengaktifkan kembali 75 pegawai KPK yang dianggap tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Sebelumnya 74 Guru Besar yang tergabung dalam wadah yang sama juga mendesak Presiden Joko Widodo bertindak atas polemik pemberhentian 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meminta Pimpinan KPK membatalkan pemberhentian tersebut.
Selama ini dunia akademik terkesan mendiamkan banyak hal yang mestinya membuat mereka bereaksi secara objektif-ilmiah, misalnya tentang usul pendirian Fakultas Kopi. Karena itu pada satusisi cukup menggembirakan adanya sejumlah orang yang mempertaruhkan moral akademiknya bersuara untuk mengoreksi permasalahan bangsa khususnya mengenai pemberantasan korupsi.
Namun, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para guru besar ini, harus saya katakana bahwa tanpa sadar mereka telah terseret pada polemik dan kontroversi masalah-masalah hilir belaka. Mereka mestinya berani memasuki dan mendiagnosis secara cermat dan menyeluruh pokok atau akar masalah sehingga tiba pada kesimpulan yang jitu dan solusionalatas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Saya menilai dengan atau tanpa ke 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)itu KPK tidak lagi memiliki kemampuan sesuai harapan pembentukannya tempo hari. Karena itu, adalah kesia-siaan belaka berkutat pada kontroversi itu.
Pada sebuah tayangan TV swasta (https://www.youtube.com/watch?v=OVsgz1lACZwsedikit) banyaknya terkuak masalah besar yang kini dihadapi KPK.
Dalam video itu, Sugiri, salah seorang dari 75 orang “korban test wawasan kebangsaan”, menit 01:31 misalnya mengungkapkan sebagai berikut:
“Saya sama pak Firli itu satu kelompok dalam test c dan sama-sama lulus test radikalisme yang dilalukan oleh Angkatan Darat. Yang menarik di tahun ini saya ditest, kok gak lulus, gitu. Bahkan Desember 2020, beberapa bulan yang lalu, saya dapat award dari Diklatpim, yaitu pelatihan kepemimpinan nasional, sebagai lulusan terbaik, begitukan.Tapi tiga bulan kemudian saya tidak lulus PNS.
Nah apakah memang ini jadi PNS itu lebih berat dibanding jadi lulusan terbaik di antara direktur semua kementerian dan Lembaga. Bahkan saya dapat public relation Indonesian Award juga tahun 2018. Dan di internasional saya banyak perjuangkan republik ini membuat standar anti-corruption Jakarta Principle on Anti-Corruption di tahun 2018 itu juga. Mewakili public ini, memberikan etalase republik ini bahwa serius dalam memberantas korupsi.
Tetapi ini bukan masalah pekerjaan bahwa saya akan dikeluarkan kemudian mengapa tidak mencari pekerjaan lain. Tidak. Ini kita menghidupkan masyarakat yang mendengarkan, pemirsa ini semuanya. Masih percaya gak sama KPK? Masih mau mengadu gak sama KPK? Gitu kan? Soalnya 75 nama ini soal kepercvayaan. Soal roh. Tentu di luar yang 75 orang itu banyak orang-orang bagus.”
Abdullah Hehamahua, mantan penasehat KPK, pada menit 04.50 mengatakan:
“Ada komisioner KPK beberapa tahun lalutidak lulus seleksi calon pegawai KPK, tetapi belakangan terpilih di DPR (menjadi komisioner KPK).”
Selanjutnya menit, 04:03, Abdullah Hehamahua menambahkan:
“Tahun 2007 KPK perlu 100 pegawai baru, kemudian yang mendaftar 27.000 orang, yang lulus cuma 45 orang. Jadi Anda coba lihat, bayangkan, begitu dahsyatnya proses seleksi di KPK. Sehingga ada komisioner KPK yang lulus di DPR ketika ikut test pegawai KPK tidak lulus. Beberapa tahun lalu dia ikut selesksi pegawai KPK tidak lulus menjadi pegawai KPK, tetapi ketika menikuti seleksi pimpinan KPK di DPR lulus. Kenapa? Karena penentuan akhir dari pimpinan KPK itu di DPR, dan DPR itu Lembaga politik. Maka kepentingannya kepentingan politik.”
Kemudian pada menit 06.20, Abdullah Hehamahua juga menegaskan:
“Itu Firli, kalau ikut test sama-sama dengan Novel, kalah Firli. Dengan Sugiri saja kalah, apalagi dengan yang lain. Dia ketika deputi penindakan, dia melanggar kode etik di KPK dan saya diundang oleh Pengawas KPK sebagai ahli untuk dimintai keterangan saya apakah yang dilakukan oleh Saudara Firli itu melanggar kode etik atau tidak. Sebelum saya diajukan pertanyaan, ditayangkan video, dan saya lihat, kemudian saya katakana kepada pengawas internal ini bukan pelanggaran kode etik. Ini pelanggaran pidana.”
Director of Global Supply Chain Compliance at International Rescue Committee, Michael Ndichu Kuria (2012), dalam sebuah tulisannya berjudul “Why do anti-corruption agencies fail?” memaparkan fakta mengejutkan tentang badan anti korupsi.
Menurutnya pembentukan badan antikorupsi terpusat justru dengan sendirinya menciptakan iklim yang membuatnya terlalu mudah bagi politisi korup dan birokrat untuk menangkap organ-organnya. Karena itu pula sekaligus dengan enteng para koruptor mampu mencegahnya mencapai tujuan yang digembar-gemborkannya sendiri.
Terlepas dari situasi betapa diharapkannya badan terpusat yang sangat istimewa itu menyelesaikan masalah, namun banyak bukti menunjukkan rakyat tetap tak pernah beranjak dari mimpi negara bersih korupsi.
Memang terdapat sangat sedikit contoh agen anti korupsi terpusat yang berhasil memerangi korupsi di dunia ini, di antaranya termasuklah Singapura dan Hong Kong. Akan tetapi meskipun Michael Ndichu Kuria member catatan penting atas sukses kedua negara itu dalam memerangi korupsi, sesunggunya ia tak melupakan aspek khusus yang jarang diingat orang, yakni bahwa Singapura dan Hongkong itu adalah negara yang relatif kecil dan sangat urban. Succes story di negara kecil tak serta-merta dapat direplikasi sama di negara berbeda karakter.
Karena pengaruh cerita keberhasilan, tentu saja kemudian kedua negara itu dianggap menjadi model terbaik dan ketika ide itu menginspirasi sebuah negara lain membentuk badan anti korupsi, sejumlah negara pengekor itu pun melahirkan sesuatu yang kemiripannya dengan praktik di Singapura dianggap sangat penting, yakni badan anti korupsinya beroleh kekuasaan dan independensinya dari undang-undang yang disahkan sebagai tanggapan atas skandal serius yang mengancam stabilitas pemerintah.
Diketahui bahwa Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong dibentuk sebagai tanggapan terhadap perselingkuhan Peter Godber 1974, sedangkan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura hanya diperkuat sebagai respon terhadap skandal tahun 1970-an yang melibatkan petugas kepolisian dalam perdagangan narkotika. Mungkin sangat mirip dengan di negara lain tertentu lainnya, bahwa krisis semacam itu memang cukup memaksa pembuat kebijakan melahirkan lembaga anti-korupsi yang independen dari kepolisian manakala polisi dipandang benar-benar sudah begitu buruk.
Menurut Michael Ndichu Kuria, model badan anti korupsi terpusat telah gagal di berbagai negara seperti Afrika dan sebagian besar dunia ketiga lainnya. Mengapa gerangan? Ia member beberapa sebab.
Pertama, upaya pembentukan badan anti korupsi terpusat itu rupa-rupanya, biasanya, dibentuk atas dorongan donor tertentu dan bukan tuntutan yang jelas dari warga negara. Fakta apa yang lazim muncul mengikutinya? Ya, donor itulah yang malah lazim memotivasi pemerintah untuk hanya membentuk lembaga yang alakadarnya saja alias lemah. Artinya hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan oleh negara donor.
Kedua, bahwa ukuran negara-negara dunia ketiga yang berusaha mengadopsi model pemberantasan korupsi di Singapura dan Hongkong, umumnya memiliki keluasan pemerintahan di pusat maupun bawahan, ditambah lagi dengan faktor-faktor demografik seperti keanekaragaman etnis yang menurut Michael Ndichu Kuria dapat dengan mudah meregangkan sumber daya badan anti korupsi yang terpusat justru kelahan-lahan yang tidak terkelola, tetapi dengan tetap berkicau sukses. Badan itu misalnya tetap berkiprah seolah berhasil, meski jika dengan jujur diaudit, ia hanya menjadi semacam bunga-bunga politik penegakan hukum dalamsuatu negara yang sama sekali tidak efektif. Badan dengan historis semacam ituakan dengan sendirinya menghindari sejumlah pantangan yang digariskan oleh bigg boss penentu politik di negeri itu.
Ketiga, absennya factor kejujuran politik. Amat sukar menemukan kemauan politik untuk menyediakan sumber daya dan independensi yang cukup kepada badan anti korupsi yang baru dibentuk. Malah, lucunya, menurut Michael Ndichu Kuria, sebagian besar dari agen terpusat ini melapor kepada pejabat yang sama yang seharusnya mereka selidiki atas kesulitan-kesulitan manajemen dan keuangannya.
Jadi dapat dibayangkan jika nafas badan pemberantasan korupsi itu sendiri ditentukan oleh pihak-pihak koruptif yang mestinya sesegera mungkin justru seyogyanya harus dikirim kelembaga pemasyarakatan. Negara dengan kepahitan pengalaman seperti itu tak pernah mampu membuat prioritas kerja yang benar dan jujur. José Ugaz, Ketua Transparansi Internasional, ketika mengantar terbitan hasil survey Indeks Persepsi Korupsi 2016 sengaja menyoroti hubungan antara korupsi dan ketimpangan, yang saling menyokong satu sama lain untuk menciptakan lingkaran setan antara korupsi, distribusi kekuasaan yang tidak merata di masyarakat, dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
Tetapi hal seperti ini akan dianggap pantang untuk menjadi prioritas kerja. Padahal di banyak negara, kata José Ugaz, orang telah kehilangan sebagian besar kebutuhan dasarnya dan tidur kelaparan setiap malam karena korupsi, sementara yang berkuasa dan korup menikmati gaya hidup mewah tanpa hukuman.
José Ugaz juga menyoroti retorika dan populisme kepemimpinan sebagai malapetaka baru. Ia berkata “Keterkaitan korupsi dan ketidaksetaraan juga member andil besar atas kemunculan pola kepemimpinan populisme. Ketika politisi tradisional gagal mengatasi korupsi, orang-orang menjadi sinis. Semakin banyak orang beralih kepemimpin populis yang berjanji untuk memutus siklus korupsi dan hak istimewa. Namun ini cenderung memperburuk – daripada menyelesaikan – ketegangan yang member andil besar atas gelombang populisme yang tak menghasilkan sesuatu kecual iilusi belaka”.
Kutipan berikut mungkin dapat menjelaskannya:
“Corruption and social inequality are indeed closely related and provide a source for popular discontent. Yet, the track record of populist leaders in tackling this problem is dismal; they use the corruption-inequality message to drum up support but have no intention of tackling the problem seriously. But, first, let’s look at what corruption has to do with inequality and vice versa.”
Keempat, percaya atau tidak, badan anti korupsi terpusat sebetulnya member politisi satu target pasti untuk dimanipulasi dan terhalang agar tidak mengekspos skema korup mereka. Ini sangat masuk akal, karena semua upaya korupsi dikoordinasikan oleh satu tubuh, semua upaya anti-korupsi dapat dengan mudah digagalkan dengan mengganggu operasinya.
Kelima, sebuah lembaga terpusat yang baru dibentuk tentulah memerlukan seperangkat undang-undang baru, infrastruktur baru, staf baru dan pembentukan birokrasi baru, yang dengan sendirinya memakan waktu lama. Ia akan asyik berteriak dan berlagak dalam seputaran isu-isu ini. Bila semua yang diperlukannya tidak diberikan dalam jumlah atau kualitas yang tepat, badan itu pun tidak dapat mencapai tujuannya. Ia akan loyo. Macan kertas. Tukang ngarang dan bermain dalam retorika akal-akalan belaka.
Hal lain yang begitu merisaukan namun kerap diabaikan begitu saja ialah State capture, grand corruption and the death of democracy. Catatan kuat pada laporan Indeks Persepsi Korupsi 2016 menyebutkan bahwa “Ketidaksamaan ekonomi ekstrim dan penangkapan politik terlalu seringsaling bergantung. Waktu tidak terkendali, institusi politik dirongrong dan pemerintah sangat melayani kepentingan elit ekonomi hingga merugikan orang biasa. Dengan kata lain, korupsi dapat berkembang ketika elit mengendalikan tuas kekuasaan tanpa pertanggungjawaban apapun.”.
Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Sumatera Utara dan Koordinator Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (nBASIS).