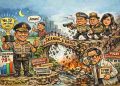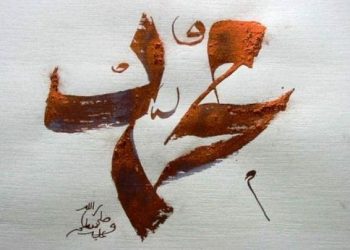UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebuah contoh bagaimana kebutuhan normatif dan konstitusional umat Islam yang memerlukan perlindungan dirumuskan, namun tidak ada niat baik untuk melaksanakannya seiring peralihan rezim (Siregar, 2019). UU itu dibuat masa SBY dan hingga sekarang tidak terealisasi yang sekaligus menandakan satu hal, bahwa bargaining position umat begitu lemah dibanding pada masa pemerintahan sebelumnya.
Banyak isyu maslahat umat dan bangsa yang begitu penting untuk menjadi urusan pranata dan organisasi keumatan. Misalnya tidakkah merasa terganggu dengan mahalnya sebuah kursi di lembaga legislatif yang mengakibatkan politik uang menjadi keniscayaan?
Bagaimana jika misalnya jumlah kursi di legislatif digandakan hingga 10 kali lipat atau lebih dan di antaranya harus ada utusan golongan-golongan yang tidak perlu dipilih agar benar-benar tereduksi penyakit demokrasi liberal yang amat merontokkan iman itu (KH Khalik Madany, Beritasatu, 2012; Mahfud MD, Republika.co.id, 2014; Rizal Ramli, Tempo.co, 2020; Refly Harun, Pikiran Rakyat, 2020) yakni tradisi kemaharajalelaan politik uang sebagaimana juga menjadi keniscayaan dalam proses pemilihan pejabat eksekutif tertinggi nasional dan daerah?
Terasa begitu hampanya harapan atas kepemimpinan yang lahir dari model pemilihan langsung yang meniscayakan bersponsor yang sejak awal memerintah hingga akhir periode kepemimpinan terus menerus berkewajiban menunaikan pembayaran utang kepada para pihak yang memerankan diri tak ubahnya debt collector?(Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, voi.id, 2020; Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Koran.Tempo.co, 2010). Organisasi keumatan tidak boleh merasa rendah diri memberi masukan bernas soal perubahan legalframework demokrasi dan pemilu sehingga pengelolaan negara dan pemerintahan dapat terus mendekati nilai-nilai keilahiyahan dan dengan demikian tak begitu sia-sia berharap akan perwujudan baldah thayyibah rabbun ghafur. (Siregar, 2018).
Bahkan jika memang sistim demokrasi yang diagungkan akan diimplementasikan sebaik-baiknya membangun bangsa, dan jika memang organisasi-organisasi keumatan keumatan itu merasa telah dan akan selalu diridloi Allah dengan pilihan sistim demokrasi itu, maka di tengah memuncaknya gagasan khilafah di antara pemikir yang sudah sangat muak dengan semua persandiwaraan politik di balik demokrasi itu, mestinya merasa terpanggil ikut memperbaiki demi maslahat (Siregar, 2018).
Pada bidang ini sangat banyak yang perlu pembenahan, misalnya bagaimana berharap demokrasi bisa berintegritas jika partai politiknya setara danga-danga antara lain karena ketakjelasan anggaran harus membiarkan korupsi meraja lela?
Baca Juga: Pemberdayaan Umat (1)
Salah satu agenda pembenahan selain mendorong demokratisasi di dalam tubuh partai adalah menganjurkan pemerintah membuat Undangundang yang menjamin alokasi dana partai, misalnya Rp 1 triliun setiap partai setiap tahun (Siregar, 2018; Rizal Ramli, Kompas.com, 2019) agar dapat mereduksi keganasan “merampok” APBN, BUMN dan APBD serta sumberdaya lainnya yang mestinya untuk kesejahteraan rakyat (Rizal Ramli, Kompas.com, 2019).
Dalam perkembangan global telah tumbuh sebuah rasisme baru Islamphobia (Siregar, 2018; Van der Valk, 2016; Tahir Abbas, 2019) yang tak terbatas pada negara-negara Barat. Anak pinak dari rasisme baru itu ialah penyesatan atas makna politik identitas, padahal identitas adalah subjek terpenting dalam politik karena definisi paling umum tentang politik yang terterima di seluruh dunia ialah who gets what kind of value, when and how. Apakah organisasi keumatan menilai kesalahan persepsi yang sudah begitu lama itu bukan bagian dari tugas dakwahnya (Siregar, 2018)?
Narasi dalam definisi politik itu diawali dengan who, yang jawabannya adalah keterangan tentang subjek politik, yakni orang, manusia, rakyat dengan segenap keberadaaan dan aspirasinya. Selama 3 dasawarsa terakhir memang kemunafikan akademisi politik di seluruh dunia tak berhasil menyembunyikan kekuatan agama-agama besar dunia yang terus berkontestasi dalam ranah kekuasaan terserah bagaimana mereka memainkan peran kontestasionalnya (Siregar, 2018).
Padahal, di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dengan mengetahui nama seseorang saja sudah segera dapat diketahui setidaknya dalam tebakan umum yang jarang meleset tentang afiliasi keagamaan yang dicampur-adukkannya dengan orientasi dan afiliasi politik. Ini bukan sesuatu yang melampaui etika dan moral politik, apalagi di negara beragama seperti Indonesia. (*)
Shohibul Anshor Siregar, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut dan Koordinator Umum n’BASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya).