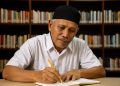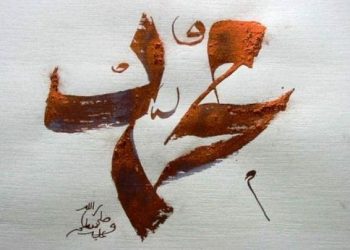Dalam sejarah birokrasi ada yang disebut gejala formalisme. Gejala ini muncul ketika ide kelembagaan pemerintahan yang diciptakan untuk tujuan efisiensi, efektivitas dan kadar rasionalitas yang menjamin terlaksananya good governance dan clean government, tetapi gagal mengimplementasikan fungsi yang diharapkan.
Sebagai gantinya muncul perilaku hipokrit dan deviasi, yakni menonjolkan formalisme baik dalam kelembagaan, narasi dan prosedur, namun pada saat bersamaan justru semakin menjauh dari efisiensi dan efektivitas. Pada tahap tertentu gejala ini pun dapat tiba pada posisi menentang ide dasar dan tujuan birokrasi.
Korps di balik birokrasi yang mengutamakan formalisme ini akan terus mendua (double speak), karena tahu kebobrokan yang terjadi namun terus mewacanakan keberhasilannya sendiri.
Saya beri satu contoh. BPJS dengan segenap kemelencengannya dari tujuan pendirian negara dan pemerintahan yakni melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesungguhnya dimaksudkan untuk menjamin tertanggulanginya masalah kesakitan seluruh rakyat.
BPJS masih sebatas urusan kesakitan, dan sesungguhnya masih belum memikirkan kesehatan karena urusannya hanya terbatas pada rumah sakit, pelayanan dokter dan resep (obat).
Tetapi pemerintah menilai tepat membebani rakyat dan ketika rakyat gagal bayar iyuran diancam dan dipelorotkan status kewarganegaraannya dengan berbagai sanksi.
Dalam praktiknya program ini ia sudah melenceng dari fungsi manifestnya itu (menjamin penanggulangan kesakitan), sehingga yang tersisa dalam pengarusutamaan program ini sekarang ialah fungsi laten (deviasi) yakni memberi peluang istimewa bagi rumah sakit dan jejaring farmakologi tertentu di Indoneia untuk menikmati keuntungan tak sah di atas penderitaan rakyat.
Aspek pengawasan dalam demokrasi yang berkembang belakangan di Indonesia memang terus mengalami penurunan fungsi dan kapasitas sejak 4 tahun terakhir. Hal itu mengakibatkan terlestarikannya fenomena formalisme yang meluas hampir ke seluruh sektor.
Dalam kasus Dana Desa yang oleh media diberitakan adanya desa siluman, secara kritis dapat diduga bahwa apa yang mengemuka itu barulah sebatas puncakgunung es. Saya yakin masih banyak masalah di luar yang mengemuka.
Diketahui proses penyaluran Dana Desa begitu rumit dan itumengesankan peluang zero tolerant to deviation (nol penyimpangan). Beberapa kementerian terlibat di dalamnya selain Kepala Daerah hingga Camat. Tetapi mengapa sejak tahun 2015 baru terungkap?
Sekali lagi, pengawasan dalam demokrasi yang trend di Indonesia sangat tak mendapat tempat. Budaya media dan LSM serta civil society gagal tumbuh sebagai penyerta kritis dan dinamis demokrasi.
Presiden tidak bisa tak bertanggungjawab dan malah dengan berjanji akan membawa KPK untuk penuntasannya, makin kelihatan bahwa Presiden gagal membereskan birokrasi yang bersih (clean) dan cakap (good).
Beberapa kasus lain yang mungkin potensil terjadi dalam kasus Dana Desa ialah tidak tepat sasaran dan asal jadi, meski dengan pertanggungjawaban keuangan (dokumen) yang terkesan justified. Ini potensi lagi sebagai penyakit formalisme. (*)

Shohibul Anshor Siregar, Dosen FISIP UMSU, Ketua LHKP PWM Sumut dan Koordinator n’BASIS.