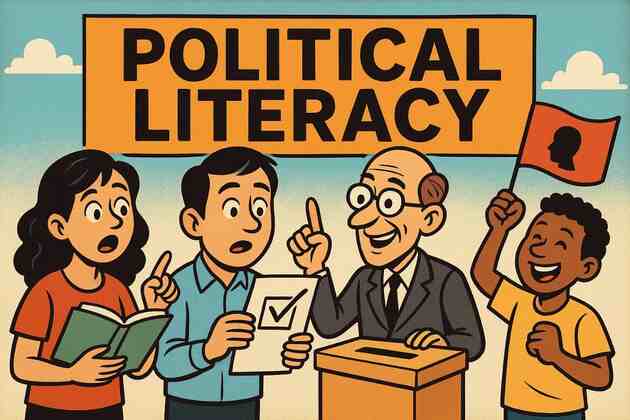Oleh: M. Risfan Sihaloho
“Literasi adalah vaksin untuk melawan para penipu dunia yang ingin mengeksploitasi ketidaktahuanmu”
Kutipan pernyataan Neil Degrasse Tyson, Astrofisikawan dan Komunikator Sains asal Amerika Serikat di atas sepertinya bisa kita adopsi mentah-mentah ke dalam dunia politik Indonesia: literasi politik adalah vaksin rakyat agar tidak terus-menerus menjadi korban tipu daya para elite yang sibuk memainkan retorika, jargon, dan janji-janji manis tanpa gizi.
Literasi politik rakyat bukan sekadar kemampuan membaca baliho, mendengar orasi kampanye, atau hafal nama partai dan simbolnya. Ia adalah kemampuan kritis rakyat untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja, siapa yang diuntungkan dari kebijakan tertentu, dan bagaimana sebuah keputusan politik bisa memengaruhi harga beras, uang sekolah anak, sampai biaya berobat di rumah sakit.
Literasi Politik di Era Digital
Era digital menghadirkan paradoks. Di satu sisi, akses informasi begitu melimpah: rakyat bisa membaca dokumen, data, berita, bahkan bocoran skandal elite hanya lewat gawai di tangan. Di sisi lain, banjir informasi ini justru bisa berubah menjadi tsunami kebohongan: hoaks, disinformasi, framing media, dan manipulasi opini oleh buzzer politik.
Literasi politik rakyat di era digital adalah kemampuan memilah mana informasi yang fakta, mana yang ilusi. Mana analisis, mana propaganda. Mana suara rakyat, mana rekayasa algoritma. Tanpa kemampuan kritis ini, rakyat bisa saja merasa sedang “berpartisipasi” padahal hanya sedang jadi objek eksploitasi digital.
Menyiasati Demokrasi Panggung
Jika kita meminjam kacamata dramaturgi Erving Goffman, politik di Indonesia seringkali tampil sebagai teater akbar. Para elite adalah aktor yang memainkan peran di front stage: penuh senyum, mengumbar janji, membungkus diri dengan jargon “demi rakyat,” tampil sederhana di depan kamera, dan pura-pura menyatu dengan rakyat kecil.
Namun di back stage, naskah yang dimainkan sungguh berbeda. Di balik layar, rakyat tidak lagi jadi pusat panggung, melainkan hanya figuran. Yang dominan adalah transaksi gelap, bagi-bagi jatah, lobi-lobi bisnis, dan kompromi kuasa. Literasi politik rakyat menjadi penting agar penonton (baca: rakyat) tidak hanya terpukau oleh panggung depan, tapi juga berani mengintip panggung belakang.
Tanpa literasi politik, rakyat hanya menjadi audiens yang pasif—tertawa, bertepuk tangan, dan menangis sesuai alur cerita yang sudah direkayasa. Padahal, politik sejatinya bukan tontonan, melainkan arena perjuangan nasib bersama.
Gerakan Liberatif
Literasi politik rakyat adalah keberanian untuk tidak lagi sekadar jadi penonton, melainkan ikut mengatur naskah. Rakyat yang melek politik sadar bahwa panggung depan sering menipu, maka mereka mulai menyorot lampu ke panggung belakang.
Dengan literasi politik, rakyat tidak lagi percaya pada aktor karismatik semata, tapi berani menguji konsistensi perannya. Mereka tidak lagi terhipnotis oleh setting panggung mewah, tapi mempertanyakan siapa produser yang membiayai pertunjukan.
Baca juga:
Kalau rakyat sudah melek politik, para aktor panggung itu kehilangan topengnya. Pertunjukan tidak lagi bisa dipentaskan hanya dengan skenario rekayasa, sebab penonton kini sudah tahu trik di balik layar.
Rakyat yang melek politik tidak lagi mudah ditipu. Mereka tahu membedakan antara “pemimpin” dan “penjual mimpi.” Mereka sadar bahwa demokrasi bukan hadiah dari elite, melainkan hak yang harus terus diperjuangkan.
Ya. Ketika rakyat sudah melek politik, para penipu itu kehilangan senjata paling ampuhnya: kebodohan massal. (*)
Penulis adalah Pemred TAJDID.ID, Pengerajin Anyaman Kata di Gerakan Rakyat Menulis (GERAM)