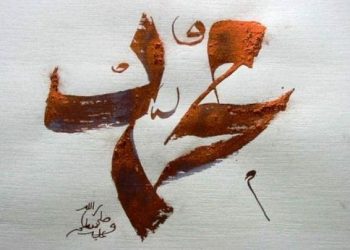Oleh: Shohibul Anshor Siregar
Abstrak
Tuan Rondahaim Saragih Garingging (wafat 1891), atau Raja Raya XIV, adalah tokoh sentral dalam perlawanan Simalungun terhadap ekspansi kolonial Belanda di Sumatra Utara. Julukan “Napoleon der Bataks” yang diberikan Belanda mencerminkan ketangguhannya dalam mempertahankan wilayah Partuanan Raya. Artikel ini menganalisis strategi politik dan militer Rondahaim, konteks historis kekuasaannya, serta makna julukan tersebut dalam narasi kolonial. Dengan merujuk pada arsip Belanda, studi etnografis, dan literatur modern, artikel ini menunjukkan bahwa perlawanan Rondahaim bukan sekadar gerakan lokal, tetapi bagian dari dinamika kompleks kekuasaan adat versus hegemoni kolonial.
Tuan Rondahaim Saragih Garingging (selanjutnya disebut Rondahaim) merupakan figur paradoks dalam historiografi Indonesia: di satu sisi, ia dihormati sebagai pahlawan lokal Simalungun; di sisi lain, ia sering absen dari narasi nasional perlawanan anti-kolonial. Sebagai Raja Raya XIV (1876–1891), ia memimpin federasi Partuanan Raya, sebuah entitas politik yang berhasil menunda aneksasi Belanda hingga akhir abad ke-19 (Joustra, 1926).
Julukan “Napoleon der Bataks” dari Belanda menggarisbawahi kecerdikan taktikalnya, sekaligus mengungkap stereotip kolonial tentang pemimpin pribumi. Artikel ini bertujuan untuk: (1) merekonstruksi peran Rondahaim dalam konteks geopolitik Sumatra Utara; (2) menganalisis strategi perlawanannya; dan (3) mengkritisi narasi kolonial yang membingkai perlawanannya.
Konteks Historis: Simalungun dan Kolonialisme Belanda
Wilayah Simalungun, yang terletak di dataran tinggi Sumatra Timur, terdiri dari federasi kerajaan kecil (partuanan) dengan sistem politik hierarkis berbasis marga (Winkler, 1912). Pada abad ke-19, Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di Sumatra melalui Traktat Siak (1858), yang mengklaim kedaulatan atas wilayah Batak. Namun, Partuanan Raya di bawah Rondahaim menolak integrasi, memanfaatkan posisi geografisnya yang terisolasi dan aliansi dengan kerajaan Karo dan Toba (Ginting, 2022).
Belanda menggambarkan Rondahaim sebagai “pengacau” yang menghambat misi pax Neerlandica. Laporan Residen Sumatera Timur (1885) menyebutkan: “Raja Raya tidak mau tunduk pada kontrak; ia mengandalkan dukungan rakyat dan medan berbukit untuk melawan” (Nationaal Archief, 1885). Perlawanan ini terjadi bersamaan dengan Perang Aceh (1873–1904), membuat Belanda kesulitan membagi sumber daya militer (Kartodirdjo, 1973).
Strategi Perlawanan Rondahaim: Diplomasi dan Gerilya
Rondahaim mengkombinasikan diplomasi dengan taktik gerilya. Ia menolak menandatangani korte verklaring (pernyataan pendek) yang melegitimasi kedaulatan Belanda, sambil memperkuat aliansi dengan pemimpin adat melalui perkawinan politik (Drakard, 1999). Pada 1883, ia memimpin serangan gerilya terhadap pos Belanda di Pematang Siantar, memanfaatkan pengetahuan topografi lokal untuk menghindari konfrontasi terbuka (Ginting, 2022).
Strategi ini mencerminkan adaptasi terhadap ketimpangan persenjataan. Seperti dikemukakan Sartono Kartodirdjo (1973), perlawanan pedesaan abad ke-19 sering mengandalkan mobilitas dan dukungan komunitas—sebuah pola yang juga terlihat di Jawa dan Aceh. Namun, Rondahaim unik karena berhasil mempertahankan otonomi tanpa perang besar, berbeda dengan Si Singamangaraja XII yang dikalahkan dalam pertempuran frontal (1907).
Julukan “Napoleon der Bataks”: Antara Kekaguman dan Stigma Kolonial
Julukan “Napoleon der Bataks” pertama kali muncul dalam laporan Belanda tahun 1880-an. Metafora ini mengandung ambivalensi: di satu sisi, mengakui kepemimpinan Rondahaim; di sisi lain, menstigmatisasi perlawanannya sebagai “ambisi kekaisaran” yang irasional (Joustra, 1926). Dalam wacana kolonial, penyebutan “Napoleon” kerap digunakan untuk pemimpin pribumi yang dianggap “liar namun cerdik”, seperti Diponegoro yang dijuluki “De Javaanse Napoléon” (Van den Bosch, 1830).
Julukan ini juga mengabaikan legitimasi kultural Rondahaim. Sebagai Raja Raya XIV, kekuasaannya bersumber dari sistem adat Simalungun dan peran marga Saragih sebagai penyandang tuan tanah (Drakard, 1999). Dengan demikian, julukan Belanda mencerminkan bias Eurosentris yang mengurangi kompleksitas kepemimpinan adat menjadi karikatur militeristik.
 Kritik terhadap Narasi Kolonial dan Kelangkaan Sumber Lokal
Kritik terhadap Narasi Kolonial dan Kelangkaan Sumber Lokal
Studi tentang Rondahaim masih bergantung pada arsip kolonial, yang cenderung mendiskreditkan perlawanannya sebagai “pemberontakan”. Sumber lokal Simalungun, seperti turiturian (cerita lisan) atau naskah pustaha, jarang dijadikan referensi. Padahal, tradisi lisan Simalungun menggambarkan Rondahaim sebagai “pertahanan terakhir martabat Partuanan” (Winkler, 1912).
Keterbatasan ini mencerminkan marginalisasi perspektif pribumi dalam historiografi Indonesia. Sebagai perbandingan, perlawanan Teuku Umar di Aceh telah diteliti melalui naskah Hikayat Perang Sabil, sementara narasi Simalungun masih terfragmentasi (Özay, 2018).
Kesimpulan
Rondahaim Saragih Garingging adalah contoh pemimpin adat yang menggunakan strategi hibrid—menggabungkan ketangguhan militer dengan diplomasi budaya—untuk melawan kolonialisme. Julukan “Napoleon der Bataks” harus dipahami sebagai produk wacana kolonial yang perlu didekonstruksi melalui sumber lokal. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menggali arsif keluarga Saragih Garingging dan mengintegrasikan sejarah Simalungun ke dalam narasi nasional Indonesia.
Daftar Pustaka
- Drakard, J. (1999). A kingdom of words: Language and power in Sumatra. Oxford University Press.
- Ginting, J. R. (2022). Contesting Sumatra: Dutch colonialism and the making of the Karo Highlands. NUS Press.
- Joustra, M. (1926). De Bataklanden: Adat, geschiedenis en geloof. Leiden: KITLV.
- Kartodirdjo, S. (1973). Protest movements in rural Java. Oxford University Press.
- Nationaal Archief. (1885). Laporan Residen Sumatra Timur. Den Haag, Belanda.
- Özay, M. (2018). Güneydoğu Asya’da sömürgecilik ve direniş [Kolonialisme dan perlawanan di Asia Tenggara]. İstanbul Yayınları.
- Winkler, J. (1912). Die Batak auf Sumatra. Berlin: Dietrich Reimer.
Penulis adalah Dosen FISIP UMSU