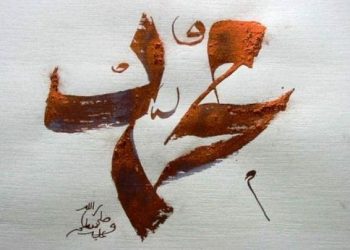TAJDID.ID~Yogyakarta || Forum Dekan Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Fordek FH & STIH PTM) Se Indonesia turut menyoroti perihal akan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) “Omnibus Law” Bidang Kesehatan.
“Kita ketahui, belakangan ini RUU Omnibus Law Bidang Kesehatan telah menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Karena itu Fordek FH dan STIH PTM Se Indonesia merasa terpanggil untuk mengkaji polemik RUU tersebut,” ujar Fordek FH dan STIH PTM Se Indonesia, Prof.Dr.Tongat,SH.,M.Hum dalam Pertemuan Nasional di Amphitarium Lantai 9 Kampus Utama Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Kamis (21/6/2023)
 Dalam kajian yang sudah dilakukan, kata Prof Tongat, pihaknya menemukan sejumlah poin krusial dari RUU Omnibus Law Bidang Kesehatan yang perlu dikritisi. Poin-poin tersebut
Dalam kajian yang sudah dilakukan, kata Prof Tongat, pihaknya menemukan sejumlah poin krusial dari RUU Omnibus Law Bidang Kesehatan yang perlu dikritisi. Poin-poin tersebut
Pertama, kendati sudah disetujui 7 fraksi untuk dibawa pada sidang paripurna, pembahasan RUU “Omnibus Law” Kesehatan nampak masih terus bersifat tertutup dan tanpa melibatkan partisipasi publik dari stakeholders penting di bidang kesehatan.
“Hingga saat ini, selain sulitnya akses terhadap draft RUU, apalagi mengakses naskah akademik dari RUU tersebut,” ungkap Prof Tongat didampingi Ujuh Juhana, SH.,MH (Sekretaris Fordek FH dan STIH PTM)
Prof Togat membeberkan, data Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Akses Kesehatan menjelaskan, bahwa dari 478 pasal dalam RUU Kesehatan, total DIM batang tubuh sebanyak 3020, sebanyak 1037 tetap. 399 perubahan redaksional, dan 1584 perubahan substansi, dalam DIM yang dibahas Agustus 2022, baru diketahui publik Maret 2023.
“Masyarakat merasa tertutup untuk tidak dapat dijelaskan (right to explained), hak untuk didengar (right to heard) dan hak untuk memberikan pendapat (right to consider) yang mana hal tersebut dituangkan dalam Putusan MK No.91/PUU/XVII/2020,” tegasnya
Kedua, polemik dalam menghadapi berbagai macam persoalan, dalam kaitannya pada Pasal 368 ayat (3) RUU Omnibus Law Kesehatan menjelaskan: Jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria: (a) penyakit yang disebabkan oleh agen biologi; (b) dapat menular dari manusia ke manusia dan/atau dari hewan ke manusia; (c) berpotensi menimbulkan sakit yang parah, kecacatan, dan/atau kematian; dan (d) berpotensi meningkat dan menyebar secara cepat.
“Pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan privasi, pengendalian, dan upaya menguatkan kapabilitas lembaga riset tersebut tidak memberikan jaminan adanya praktik bio-terorisme,” kata Prof Tongat.
Dijelaskannya, istilah bio-terorisme muncul akibat penyebarluasan penyakit/wabah yang tidak dapat dikendalikan. Bioterorisme melibatkan senjata biologi yang dapat berbahaya bagi kemanusiaan dan warga yang dapat digunakan oleh kelompok teroris baik by design maupun yang lahir organik.
“Hal ini penting diantisipasi dengan sejauh mana kesiapan negara dalam menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan instrumen penelitian dan spesimen yang memadai, serta kebijakan yang betul-betul penting dalam melindungi keselamatan warga negara,” tegas Prof Tongat.
Ketiga, ada hal penting terkait dengan genom dan privasi, walaupun tidak tersurat secara jelas keberadaan BGSi (Biomedical & Genome Science Initiative) namun dalam DIM Pasal 361 ayat 2 tentang Pengalihan dan penggunaan material dalam bentuk spesimen klinik dan materi biologis, muatan informasi dan/atau data ke luar wilayah Indonesia, memberi peluang lebih besar penyalahgunaan karena tidak terbatas pada pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan di Indonesia tapi juga menyangkut cara atau metode yang tidak dapat dilakukan di Indonesia.
“Kesemua hal itu dapat menyebabkan terjadinya bio terorisme seperti tersebut di atas. Oleh karena sangat mungkin terjadi penyimpangan dalam MTA (Material Transfer Aggrement) sehingga data genetik orang Indonesia (Bio Bank) dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga bahkan pengembangan Bio Weapon dengan data genetik sudah menjadi isu global. Hal dimaksud di atas berkaitan dengan genom dan privasi, justru tidak cukup diatur dan tidak ditampung dalam RUU “Omnibus Law” Kesehatan,” sebut Prof Tongat.
Keempat, disisi lain kemandirian bangsa dalam riset bioteknologi sudah dimulai oleh Lembaga Eijkman sayangnya kemudian dilebur ke dalam BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) tanggal 15 Mei 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021.
Kelima, fasilitas penganggaran dalam rangka melindungi akses kesehatan yang komprehensif dan pelayanan yang memadai, hal tersebut dilindungi dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Prof Tongan mengungkapkan, pada rumusan Pasal 420 RUU Omnibus Law Bidang Kesehatan memiliki mandat untuk menyediakan anggaran minimal (spending mandatory) sebesar 10% minimal harus dijamin dan dilaksanakan. Dalam perkembangannya usulan di atas dihapuskan padahal hak atas kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi.
“Anggaran kesehatan itu seharusnya dianggarankan melalui APBN maupun APBD dan idealnya, jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh prosentasenya harusnya 15% dan digunakan untuk fasilitas kesehatan, obat, jaminan kesehatan, dan sebagainya secara menyelurruh bagi warga Indonesia, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (*)