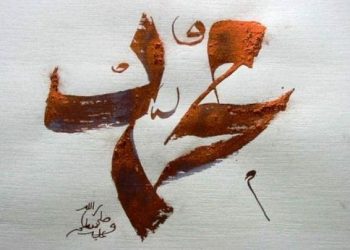Oleh: M. Risfan Sihaloho
Pengerajin Anyaman Kata di Gerakan Rakyat Menulis (GERAM)/ Demonstran ’98
Demonstrasi selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Ia adalah “panggung jalanan” tempat rakyat bersuara lantang ketika suara di gedung-gedung megah tak lagi didengar. Tapi ada satu hal yang selalu muncul setiap kali demo berujung ricuh: pertanyaan klasik, “Apakah ini murni suara rakyat atau ada yang menunggangi?”
Pertanyaan ini sebenarnya sederhana, tapi jawabannya rumit, karena politik di negeri ini lebih sering berisi drama ketimbang logika.
Namun yang jelas, demo besar di Indonesia hampir selalu punya dua wajah: satu wajah rakyat yang benar-benar marah, satu wajah bayangan yang ikut nimbrung entah untuk memperlemah gerakan, mengubah narasi, atau memanfaatkan momentum.
Baca juga: Ketika yang Lemah Melawan
Pola Aksi
Dalam literasi gerakan sosial, seperti dipaparkan Sidney Tarrow dalam “Power in Movement”, aksi massa biasanya lahir dari tiga hal: ketidakadilan yang menumpuk, solidaritas kolektif, dan kesempatan politik. Artinya, ketika rakyat sudah muak, sementara kanal resmi penyalur aspirasi tersumbat, maka mereka akan turun ke jalan.
Namun, kita sering melihat pola yang mirip: Aksi damai di awal. Spanduk dipampang, orasi disampaikan, yel-yel diteriakkan dan nyanyian perlawanan dikumandangkan. Sampai disini semua masih dalam batas normal.
Kemudian tiba-tiba muncul provokasi yang membuat eskalasi makin panas. Entah ada yang lempar batu, bakar ban, atau seruduk pagar kawat berduri.
Tatkala suasana kian memanas, massa pun mulai liar dan tak terkendali. Kericuhan pun pecah. Massa jadi agresif dan beringas. Polisi balas dengan gas air mata dan water canon. Massa terpancing emosi, dan terjadi chaos. Ujungnya media menulis headline: “Aksi Damai Berakhir Ricuh.”
Murni atau Ditunggangi?
Apakah ini spontan? Tidak selalu. Dalam studi komunikasi politik, dikenal istilah framing conflict. Kericuhan seringkali muncul bukan dari massa inti, tapi dari “pemain bayangan” yang sengaja hadir untuk mengubah narasi aksi.
Aksi murni biasanya ditandai dengan konsistensi tuntutan. Orasi fokus pada isu, massa relatif kompak, dan jika ada gesekan, masih bisa dikendalikan oleh koordinator lapangan.
Sedangkan aksi ditunggangi punya tanda lain: tuntutan melebar ke mana-mana, ada kelompok tak dikenal ikut nimbrung, muncul kekerasan yang tidak sesuai dengan spirit gerakan awal.
Namun yang pasti, bukan sesuatu yang gampang untuk memastikan sebuah aksi demonstrasi dijalanan murni atau ditunggangi.
Tentang hal ini, pengamat politik, Arbi Sanit, pernah bilang, “Di Indonesia, hampir mustahil membedakan antara gerakan murni dan rekayasa. Karena begitu massa berkumpul, peluang untuk ditunggangi selalu terbuka.”
Kemudian diperkuat sosiolog politik, Ariel Heryanto, yang mengatakan, bahwa dalam politik jalanan, sulit membedakan mana spontanitas rakyat, mana rekayasa. Justru, menurutnya yang paling penting adalah menelusuri siapa yang diuntungkan dari kekacauan itu.
Siapa Penunggang Sesungguhnya?
Lucunya, istilah “ditunggangi” sering jadi mantera ajaib pemerintah. Begitu ada aksi besar, selalu ada suara pejabat berkata: “Ini pasti ada yang menunggangi.”
Pertanyaannya: siapa yang sebenarnya menunggangi siapa? Apakah elite menunggangi rakyat untuk kepentingan politik mereka? Ataukah rakyatlah yang sedang berusaha menunggangi momentum elite? Atau jangan-jangan yang menunggangi adalah opini kelompok tertentu lewat framing di media yang selalu lapar rating?
Dalam bahasa satir, demonstrasi di Indonesia kadang lebih mirip arena pacuan kuda: rakyat jadi kuda, tuntutan jadi pelana, dan penunggangnya bisa siapa saja—partai, oligarki, aparat, atau kelompok asing.
Baca juga: Unstoppable
Analisis
Untuk memahami aksi demonstrasi di jalanan, ada sejumlah pisau analisis yang bisa pakai.
Pertama, analisis struktural. Demo lahir karena ada ketidakadilan nyata: harga melambung, kebijakan elitis, atau korupsi yang menggerogoti. Ini basis murni.
Kedua analisis kultural. Setidaknya, budaya protes di Indonesia sudah melekat sejak era reformasi. Tapi juga ada budaya infiltrasi—aktor bayangan yang suka nimbrung.
Ketiga, analisis aktor. Siapa yang hadir? Apakah ada kelompok tak dikenal yang tiba-tiba jadi “pemicu” kerusuhan? Kalau iya, besar kemungkinan ada penunggang.
Keempat, analisis narasi. Bagaimana media, pejabat atau pihak-pihak tertentu merespons? Kalau narasi “ditunggangi” langsung muncul sejak awal, justru itu tanda ada upaya menggiring opini.
Kelima, analisis politik kekuasaan. Aksi massa sering dijadikan bargaining politik. Demo sangat mungkin bisa jadi “alat negosiasi” elite untuk tekan lawan.
Penutup
Pada akhirnya, membaca pola demo di Indonesia mirip membaca naskah sinetron: ada tokoh utama (massa), ada antagonis (provokator), ada figuran (aparat), dan ada sutradara tak terlihat (elite politik).
Demo 25 Agustus 2025 memperlihatkan satu hal: ternyata rakyat masih punya energi untuk bersuara, tapi suara itu selalu terancam ditelan skenario para hantu penunggang.
Apakah murni? Bisa iya. Apakah ada yang menunggangi? Bisa juga. Tapi yang pasti, rakyat jarang sekali jadi penunggang. Mereka lebih sering jadi tunggangan—yang digiring, digas, atau dibiarkan lelah di jalanan. (*)