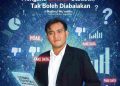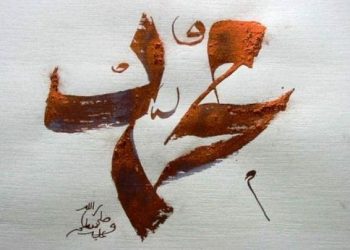Oleh: Nashrul Mu’minin
Content Writer Yogyakarta
Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa PSI (Partai Solidaritas Indonesia) bukanlah partai keluarga, meskipun sang anak—Kaesang Pangarep—kembali ditetapkan sebagai ketua umum lewat mekanisme e-voting. Klaim ini disandingkan dengan jargon “partai super terbuka” dan penyebutan PSI sebagai partai “Tbk” yang dikatakan mencerminkan kepemilikan kolektif oleh para anggota. Retorisnya terdengar progresif—mendorong kesan modernitas, demokratis, dan transformatif.
Namun, di balik kemasan modernitas tersebut, muncul kritik tajam dari berbagai pihak. Guntur Romli dari PDI-P, misalnya, menilai pernyataan Jokowi sebagai hal yang paradoks: “Kalau Jokowi bilang PSI bukan milik keluarga, apa dia enggak punya malu? Menyampaikan hal itu di depan anaknya.” Kritik ini tidak semata menyasar retorika, tetapi menyentil legitimasi pemilihan internal PSI yang dianggap mirip “sepak bola gajah”—permainan yang hasilnya sudah diketahui sejak awal. Isu netralitas dan transparansi dalam proses e-voting pun mulai dipertanyakan.
Mengklaim sebagai partai milik kader semua dan bukan milik keluarga memang menarik, apalagi didukung teknologi pemungutan suara modern. Namun, bila jabatan ketua umum secara konsisten dijatuhkan kepada Kaesang, dan tokoh internal seperti Jeffrie Geovanie mulai menyuarakan istilah “darah Jokowi” dalam PSI, maka jargon “terbuka” justru terlihat sebagai kamuflase dari dominasi keluarga presiden. Apalagi, kehadiran Jokowi sebagai dewan pembina yang berdiri di hadapan kader memberi kesan kuat bahwa PSI masih sangat bergantung pada figur sentral keluarga.
Ironi kian terasa ketika semangat transparansi justru kontradiktif dengan struktur kekuasaan internal partai. Publik patut bertanya: apakah e-voting benar-benar mencerminkan demokrasi sejati atau hanya etalase teknologi tanpa substansi check and balance? Demokrasi internal bukan sekadar soal siapa yang menang, tetapi tentang proses pemilihan yang adil, terbuka, dan bebas dari pengaruh dominasi keluarga politik.
Inti persoalan terletak pada budaya politik partai: apakah keberadaan “anak presiden” dalam posisi puncak yang diulang terus-menerus mencerminkan kemajuan demokrasi internal, atau sekadar reproduksi elit lama dalam format digital yang lebih modern? Jika PSI benar-benar ingin dikenal sebagai partai baru yang berbeda, maka inilah waktunya untuk membuktikan hal tersebut—bukan dengan gimmick, tetapi melalui reformasi nyata.
PSI harus berani menempuh langkah korektif jika ingin tetap relevan dan dipercaya publik sebagai pelopor regenerasi politik Indonesia. Reformasi itu mencakup rotasi kepemimpinan, pembatasan peran keluarga dalam struktur inti, serta pelembagaan sistem seleksi ketua umum yang independen dan kredibel. Tanpa langkah konkret tersebut, jargon “super terbuka” hanya akan menjadi hiasan politik, sementara partainya perlahan kehilangan momentum dan kepercayaan publik. (*)