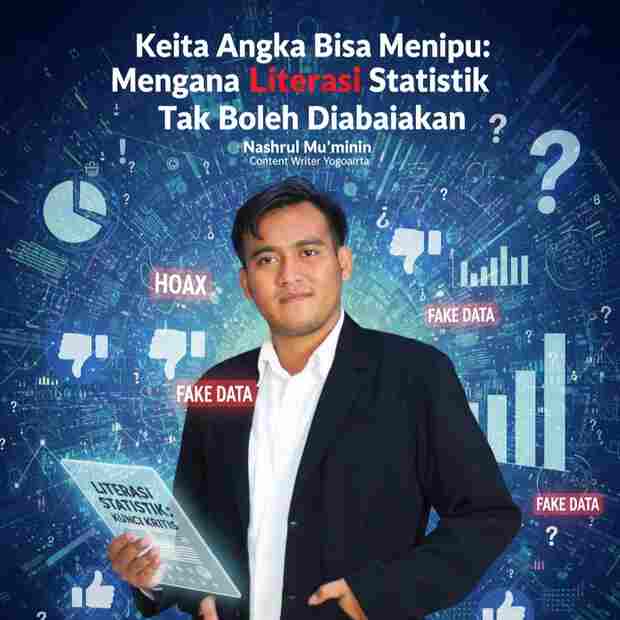Oleh: Nashrul Mu’minin
Content Writer Yogyakarta
Di era digital saat ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada derasnya arus informasi yang seakan tak terbendung. Media sosial, portal berita, hingga percakapan sehari-hari menyajikan data dan angka yang sering kali diklaim sebagai fakta. Namun, di balik banjir informasi tersebut, muncul masalah mendasar: rendahnya literasi statistik masyarakat. Kondisi ini membuat banyak orang mudah terkecoh oleh angka yang tampak meyakinkan, padahal jika ditelaah lebih jauh, data tersebut bisa saja dimanipulasi atau dipresentasikan tanpa konteks yang jelas.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2021 hanya sekitar 28,5% masyarakat Indonesia yang merasa percaya diri membaca tabel, grafik, atau data persentase. Pada April 2022 angkanya naik menjadi 31,2%, lalu Mei 2023 mencapai 32,7%. Pertumbuhan masih berlanjut pada Juni 2024 dengan 34,1%, dan pada Juli 2025 baru menyentuh 36,8%. Dalam kurun waktu lima tahun, peningkatan tersebut rata-rata hanya sekitar 2% per tahun. Meski positif, laju perbaikan ini jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan penyebaran informasi di media digital.
Tujuan utama dari peningkatan literasi statistik bukanlah sekadar agar masyarakat bisa membaca angka, melainkan mampu memahami makna dan konteks di balik data tersebut. Kasus pada Agustus 2022 menjadi contoh nyata. Beredar luas klaim bahwa angka pengangguran menurun hingga 20%, membuat masyarakat percaya bahwa kondisi ekonomi membaik. Namun, penurunan tersebut ternyata bukan karena bertambahnya lapangan kerja formal, melainkan akibat perubahan metode pencatatan yang memasukkan tenaga kerja informal ke dalam kategori “bekerja”. Tanpa kemampuan literasi statistik, masyarakat dengan mudah termakan framing data semacam ini.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada November 2023 melaporkan bahwa 62% hoaks yang tersebar di media sosial mengandung angka atau klaim statistik. Dari jumlah tersebut, lebih dari 70% masyarakat yang membacanya percaya begitu saja hanya karena ada angka yang menyertainya. Hal ini membuktikan bahwa data numerik sering digunakan sebagai alat manipulasi psikologis, karena angka memberi kesan objektif dan ilmiah meskipun kenyataannya bisa menyesatkan.
Evaluasi dari periode 2021–2025 menunjukkan bahwa meskipun literasi statistik mengalami peningkatan, kesenjangan pemahaman antara masyarakat perkotaan dan pedesaan masih besar. Program sosialisasi yang dilakukan BPS dan Kominfo cenderung lebih efektif di kota-kota besar, sementara daerah terpencil masih minim akses pelatihan atau edukasi terkait pemahaman data. Selain itu, kurikulum pendidikan formal pun belum sepenuhnya menekankan literasi statistik sebagai keterampilan hidup yang penting di era digital.
Menurut saya, kesimpulannya jelas: literasi statistik bukanlah kemampuan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat modern. Jika literasi ini dikuatkan, masyarakat akan lebih kritis dalam menerima informasi, tidak mudah tertipu oleh hoaks, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat perlu bergandengan tangan agar pemahaman statistik tidak lagi dianggap sekadar urusan akademisi, melainkan keterampilan penting untuk semua orang di tengah derasnya arus informasi. (*)