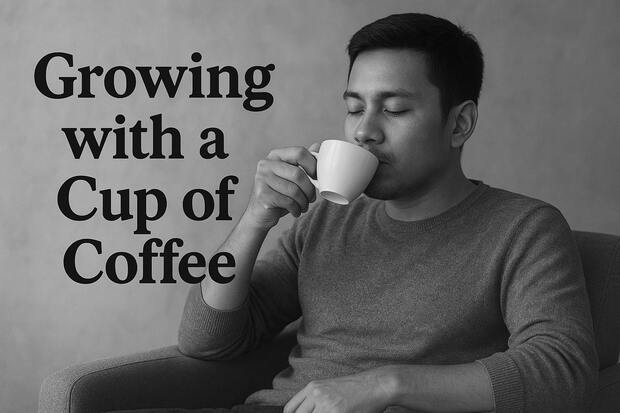Oleh Mujahiddin
(Associate Professor bidang Studi Pembangunan di FISIP UMSU)
Satu pagi, seorang anak bertanya pada ayahnya.
“Pa, apakah pohon itu adalah makhluk hidup?”
Papanya menjawab dengan sederhana; “Ya, pohon itu makhluk hidup.”
Tapi pertanyaan anak-anak itu tidak pernah bisa berhenti sampai sesuatu yang ia inginkan atau yang ia cari bisa terjawab di kepalanya. Pertanyaan itu terus berlanjut dengan mekanisme logika khas anak-anak.
“Jika pohon itu makhluk hidup, kenapa dia tidak bicara seperti manusia pa?” tanya si anak dengan kritis.
“Hewan juga makhluk hidup, tapi dia tidak bisa bicara” jawab ayahnya singkat dengan nada yang kawatir.
“Bukannya hewan bisa bicara pa, seperti kucing yang bilang meong?” timpal si anak kembali.
“Itu bukan bicara, itu bersuara. Seperti lembu, kambing, gajah dan lain sebagainya. Mereka hanya bersuara khas mereka. Kita tidak mengerti maksudnya, mungkin sesama mereka juga tidak mengerti maksudnya. Mereka hanya bersuara saja tanda. Jadi pahamkan?” Ayah dari anak tersebut mulai menjawab dengan penekanan agar tidak ada lagi pertanyaan tambahan.
Dan supaya dialog bisa berakhir cepat, ayah dari si anak memberikan jawaban tambahan.
“Jadi begini, kita manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena iya terus tumbuh, bergerak dan menjadi sesuatu sesuai fungsinya sampai akhirnya ia mati, tewas dan hancur. Jadi pohon itu, meski ia tidak bisa bicara, tetapi iya bertumbuh; tidaknya hanya menjulang ke atas tetapi akar juga menguat kebawah, mencari makan (nutrisi) agar batang pohonya kuat, ranting-rantingnya bisa menghasilkan buah dan daun yang bagus. Kamu paham ya? Kamu pernah lihat akar pohon kan?”
“Iya, aku pernah lihat akar pohon. Seperti itu kan?” Si anak menunjuk salah satu pohon besar yang beberapa akarnya terlihat di atas permukaan tanah.
“Iya. Itu hanya sebagian yang tampak. Akar pohon bisa menjalar ke mana-mana. Tapi pada umumnya akar akan ke bawah, untuk mencari makan dan menjadi penyanggah agar pohonnya tetap kuat. Tidak gampang tumbang jika terkena angin kencang” terang ayah si anak yang sudah mulai kehabisan penjelasan.
Menemui Simone Weil
Percakapan antara seorang anak dengan ayahnya di atas tadi, mengharuskan kita mereview kembali bagaimana pohon (sebagai satu subjek makhluk hidup) juga sering ditafsirkan dengan pemaknaan-pemaknaan lainnya. Beberapa filsuf bahkan memposisikan pohon sebagai satu contoh simbol kebijaksanaan hidup di dunia. Aristoteles misalnya, ia memberikan pengajaran bahwa sejatinya manusia seperti biji yang harus ditanam dan dirawat di tempat yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pohon besar yang sesuai dengan jenisnya.
Selain Aristoteles, ada juga filsuf abad ke-20, bernama Simone Weil yang menggunakan pohon sebagai simbol yang kuat tentang kondisi manusia di alam semesta. Baginya, pohon lebih dari sekedar metafora; ia mewujudkan hubungan antara surga dan bumi, yang ‘sakral’ dan yang ‘profan’ sehingga mencerminkan dualitas dalam diri manusia masing-masing. Dalam pikirannya, pohon melambangkan dualitas yang hakiki, yakni ‘berakar di bumi namun menjulang ke langit.’ Ia seolah menghubungkan antara dunia material dan spiritual.
Pada konteks ini, Weil melihat dualitas tersebut sebagai sesuatu yang saling bertentang tetapi tidak dalam kerangka saling memecah belah. Ia adalah jalan/upaya menuju keseimbangan personal dan kolektif. Secara sederhana, Weil ingin mengatakan bahwa; ‘pohon mengingatkan setiap orang untuk berakar kuat sambil tetap terbuka terhadap misteri transendensi.’
Yang Awal & Siklus Eksistensial
Yang awal dari pohon adalah biji pohon. Ia menjadi awal mula kehidupan, harapan, potensi pertumbuhan, dan keterhubungan yang berkelanjutan. Hal ini memberikan makna bahwa setiap hal yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil dan rapuh. Di sinilah siklus eksistensialisme yang saling berhubungan dimulai; proses biji menjadi pohon dan akhirnya menghasilkan buah yang kembali menjadi biji, dapat dilihat sebagai siklus penciptaan diri yang berkelanjutan. Manusia, melalui kesadaran mereka, menciptakan makna dan kemudian meneruskan ‘benih’ makna tersebut kepada generasi selanjutnya.
Tetapi tidak semuanya bisa berjalan lancar. Eksistensialisme pada diri manusia membuka ruang bagi terbentuknya kebebasan untuk memilih dan berkehendak. Ia tidak fungsional sesuai dengan makna apa yang diturunkan oleh generasi sebelumnya. Manusia tumbuh, menafsir dan mengkonstruksi diri sendiri dengan akal pikiran dan praktik sosial yang ada disekitarnya. Karena manusia menciptakan esensinya sendiri, mereka memiliki kebebasan mutlak untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus dihadapi dalam sebuah dunia yang tanpa makna bawaan. Tuhan sebagai pencipta manusia bahkan sejak awal telah menyadari hal tersebut dan telah memberikan peringatan dengan tegas; “Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata (Surah Yasin ayat 77)”.
Biji Hitam & Eksistensialisme
Biji hitam adalah simbol lain untuk menggambarkan kopi. Minumnya yang memiliki sejarah panjang di dalam kehidupan manusia. Para filsuf, tokoh agama dan semua orang mencicipi kopi sebagai minuman sekaligus sebagai teman. Disebut sebagai teman karena kopi memberikan dorongan semangat, fokus, dan inspirasi bagi banyak orang dalam aktivitas sehari-hari seperti belajar atau bekerja.
Satu di antara filsuf yang gemar dengan kopi adalah Søren Kierkegaard. Ia dijuluki sebagai bapak eksistensialisme. Tidak banyak yang mengatahui jika ia seorang penggemar kopi. Ia minum kopi sejak dini hari, dan kopi selalu tersedia di meja tempatnya menulis. Bagi Kierkegaard, kopi lebih dari sekadar minuman. Kopi menjadi ritual, momen refleksi, dan sumber inspirasi. Dengan minum kopi, ia dapat memikirkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial dalam hidup. Rasa kopi yang kuat dan kaya seolah membangkitkan dan mempertajam pikirannya.
Dan benar saja, meminum kopi bisa memicu pikiran eksistensialisme kerena efek psikoaktif kafein yang merangsang otak. Tidak hanya itu, budaya mengopi di banyak komunitas masyarakat juga dapat menciptakan dialog yang reflektif dan mendalam. Ia menjadi wadah percakapan tentang makna kehidupan dan eksistensi, serta ruang berbagi ide.
Di sinilah letak pentingnya bertumbuh bersama segelas kopi (growing with a cup of Coffee). Mungkin kalimat ini tidak memiliki makna secara harfiah. Namun secara metaforis (dengan budaya minum kopi yang terus ramai) growing with a cup of Coffee bisa berarti menikmati pertumbuhan secara personal, professional, dan berkembang seiring waktu dengan kopi sebagai pendamping. Meski hitam (terkadang juga pahit), tetapi tidak ada kemunafikan di dalamnya. Ia justru mendorong hadirnya pikiran-pikiran eksistensial.
Pentup
Biji, pohon dan segala sesuatu yang ada disekitarnya adalah bagian dari dinamika eksistensial itu sendiri. Dalam diri manusia juga begitu, bertumbuh dan berkuasa adalah kendak yang ingin terus dilakukan bahkan dengan cara-cara manipulatif dan kasar; menikam dari belakang, memfitnah, menghasut, dan mengubur harapan orang-orang yang menjadi lawan eksistensialnya. Dalam proses itu, terkadang manusia lupa, tidak selamanya pertarungan bisa dimenangkan, tidak selamanya musik pesta berdentum keras dan menghadirkan joget kegembiraan. Semua bisa berakhir dengan mekanisme siklus eksistensialisme tadi. Jangan dikira yang dikubur itu akan mati; ia justru bisa hidup dan bertumbuh seperti biji pohon. Bahkan bangkai yang dikubur sekalipun, ia tetap menghasilkan nutrisi bagi tumbuhan-tumbuhan berikutnya. (*)